Seperti yang sudah disimak dalam tulisan-tulisan sebelumnya mengenai awal Abad Pertengahan, salah satu semangat utama pemikiran yang lahir dari para intelektual zaman itu adalah rekonsiliasi antara Kristen dan tradisi Pagan yang mendahuluinya. Tradisi Kristen pada awalnya didominasi filsafat Plato; itulah sebabnya St. Agustinus—salah seorang filsuf besar Gereja awal—juga mengambil sikap kontra terhadap karya sastra. Bersama dengan misi rekonsiliasi ini, Gereja mulai menggeser batu pijakan filsafatnya pada pemikiran Aristoteles (yang dikenal memilih “jalan tengah” dalam pergulatan soal kamar kerja filsafat dan seni). Hal ini terutama berangkat dari kenyataan bahwa tradisi Kristen punya keterkaitan yang erat dengan tradisi intelektual Yunani Kuno (Pagan).
Filsuf skolastik Kristen yang akan saya ulik sedikit pemikirannya dalam tulisan ini termasuk salah seorang yang melanjutkan upaya rekonsiliasi tersebut. Di kemudian hari, ia dikenal sebagai filsuf terbesar Gereja Katolik; pemikiran-pemikirannya diteruskan ke dan dilestarikan di institusi pendidikan Katolik.
St. Thomas Aquinas (1225-1274)
Thomas Aquinas lahir dari keluarga Katolik yang taat. Nama “Aquinas” merujuk pada nama daerah dari mana ia berasal, yakni Aquino. Sejak usia lima tahun, Thomas sudah dilepas bapak dan ibunya untuk dititipkan di sebuah biara Benedictus agar jadi biarawan. Keinginan orang tuanya itu terkabul; Thomas Aquinas masuk Ordo Dominikan. Biarawan Ordo Dominikan mendevosikan diri untuk jadi miskin dan hidup sederhana. Mereka memusatkan karya religiusnya dalam dunia pengetahuan dan pengajaran dengan satu visi: merekonsiliasi ajaran Aristoteles dan Kristus. Tampaknya, fokus kerja akademis ordo inilah yang banyak memengaruhi karya-karya Aquinas.
Thomas Aquinas meninggal di usia 49 tahun. Karya-karyanya semasa hidup memang saat ini berkontribusi besar dalam ajaran Gereja, tetapi pada masa itu pemikiran Aquinas sempat ditentang habis-habisan oleh kaumnya sendiri karena terbilang kontroversial dan radikal. Tidak mengherankan bila pengangkatannya menjadi santo oleh Gereja baru disahkan 49 tahun sesudah kematiannya; gelar “Doktor”[1]-nya bahkan baru diberikan oleh Gereja pada tahun 1567—hampir 300 tahun setelah kematiannya.
Sebagai seorang biarawan sekaligus pemikir, selama hidupnya Aquinas menulis sejumlah karya. Dua judul terbesarnya adalah Summa Theologiae dan Summa contra Gentiles. Kedua karya ini bertemakan pembuktian keberadaan Tuhan dan kebenaran Kristen. Dalam karya-karya ini, Aquinas memaparkan hierarki ilmu dan meletakkan teologi sebagai pusat dari segala ilmu pengetahuan. Sebagian dari buah pikirnya ini ternyata berada di jalan yang beriringan dengan berjayanya tradisi gramatika sebagai tulang punggung budaya literasi. Perjumpaan jalan itu akan saya paparkan sedikit dalam bahasan selanjutnya.
Antara Nalar dan Wahyu
Topik ini tidaklah asing dalam perbincangan soal agama. Kredo bahwa ilmu pengetahuan dan ajaran agama tidak akan pernah berpijak pada dasar yang sama apalagi saling cocok satu sama lain kerap kali jadi argumen yang digunakan untuk memungkas perdebatan soal upaya rasionalisasi agama dan, juga sebaliknya, peng-agama-an rasio. Perdebatan ini ternyata sudah tua umurnya. Thomas Aquinas dan banyak pemikir serta teolog Abad Pertengahan telah berurusan dengan persoalan yang persis sama dan membangun pendiriannya masing-masing.
Apa pandangan Aquinas tentang ini? Nalar (reason) dan wahyu (revelation) telah dipisahkan menjadi dua domain berbeda dalam tradisi pemikiran yang terpengaruh rasionalisme Aristotelian. Pandangan semacam ini, disebutkan oleh Habib, masuk dalam dinamika intelektual Gereja salah satunya melalui para filsuf Islam. Aquinas sepakat dengan pembedaan ini, tetapi poin yang menandai posisinya adalah argumen bahwa keduanya tidaklah kontradiktif, melainkan harus sesuai satu sama lain. Persis di titik inilah Aquinas meletakkan teologi sebagai jembatan yang menghubungkan antara nalar dan wahyu. Teologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan wahyu terkait keimanan. Dan justru melalui ilmu pengetahuan inilah, “iman” yang tidak kelihatan itu dapat dipelajari dan dimengerti. Aquinas percaya bahwa tujuan akhir dari hidup manusia adalah “mengenal Tuhan”, sehingga teologi adalah ilmu pengetahuan puncak yang mampu mengakomodasi kebutuhan itu.
Secara lebih spesifik, Aquinas bahkan membedakan antara nalar dan intelektualitas. Kedua hal ini berfungsi untuk jenis ilmu pengetahuan yang berbeda. Nalar adalah peranti untuk memahami ilmu pengetahuan alam dengan cara kerja melihat banyak hal demi mencapai satu kebenaran yang tunggal. Sementara ilmu pengetahuan ilahiah—teologi—membutuhkan intelektualitas yang bekerja dengan mode menangkap banyak hal dalam satu kebenaran sederhana (baca: Tuhan). Bagi Aquinas, “God is the end of each thing, and hence each thing, to the greatest extent possible to it, intends to be united to God as its last end.” Dalam kalimat tersebut, barang sekecap dua kecap, saya mengingat konsep Roh Absolut dari Hegel. The Divine, atau yang dalam konteks teologi Aquinas ini merujuk pada Tuhan, mengejawantah dalam bentuk material, yang salah satunya adalah manusia. Dan pada akhirnya, segala ciptaan ini akan menuju kembali pada sumbernya yang tunggal.
Terkait dengan pandangan itu, hierarki ilmu pengetahuan versi Thomas Aquinas tidak menyingkirkan ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan nalar. Ilmu pengetahuan alam justru “menyiapkan” manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang ilahiah. Habib menyebutkan bahwa jalan ini menyatukan dua pandangan berbeda mengenai campur tangan Tuhan dalam terselenggaranya alam raya: Tuhan memang mengatur semesta, tetapi hal itu dilakukan dengan cara mengakomodasi hukum-hukum sains yang menjadi dasar operasi alam raya.
Dengan posisi teologi sebagai pusat sekaligus puncak dari ilmu pengetahuan manusia, Aquinas berupaya membantu merumuskan argumen logisnya akan keberadaan Tuhan sebagai penyelenggara semesta. Tema ini maktub dalam Summa Theologiae. Bukti pertama keberadaan Tuhan adalah bahwa untuk menggerakkan alam semesta ini, dibutuhkan sesuatu yang menjadi penggerak yang sendirinya tidak ikut bergerak. Aquinas menyebutnya Unmoved Mover. Dengan logika serupa, hadir bukti kedua, yakni mestinya ada sesuatu yang menjadi “penyebab” segala sesuatu, dengan dirinya sendiri tidak disebabkan oleh hal lain yang mendahuluinya. Posisi ini disebut First Cause. Ketiga, pasti ada sumber utama dari segala hal di alam semesta ini, yakni Primal Source. Bukti keempat adalah adanya relativitas jenis dan derajat kesempurnaan tertentu yang dilekatkan manusia pada segala hal. Oleh karena itu, semuanya ini pastilah berasal dari sesuatu yang memiliki kesempurnaan absolut atau (Absolute) Perfection. Bukti terakhir, ialah bahwa segala hal yang tercipta ini pasti dimaksudkan untuk memiliki fungsi atau peran tertentu. Nah, berarti, ada “sutradara” yang mengarahkan semuanya ini, termasuk benda tak bernyawa sekalipun.
Upaya menjelaskan keberadaan Tuhan ini terkait erat dengan pemosisian dunia material dalam mekanisme memahami ilmu pengetahuan ilahiah versi Aquinas. Sejalan dengan Aristoteles, Aquinas melihat elemen-elemen dunia material sebagai bentuk partikular dari universalitas yang transenden. Melalui yang-partikular inilah jalan menuju pemahaman akan yang-universal itu terbuka. Eksistensi elemen dunia material merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi (sekaligus esensi) The Divine. Pandangan inilah yang menjadi dasar dari estetika Aquinas yang akan secara ringkas dijabarkan dalam bagian selanjutnya.
Yang-Transenden sebagai Sumber Keindahan yang Inheren
Penggambaran hubungan manusia sebagai makhluk ciptaan dengan Tuhan sebagai pencipta, dalam pandangan Aquinas menyiratkan adanya pewarisan sifat-sifat (nature) tertentu dalam proses penciptaannya. Ia menyebut nature ini sebagai “the transcendentals”—dalam tulisan ini diterjemahkan menjadi “yang-transenden”—yang meliputi tiga karakteristik utama: “one”, “true”, dan “good” (yang terakhir juga kerap disebut “beauty”). Sifat-sifat ini dimiliki oleh semua makhluk (ciptaan) sebab proses penciptaan sendiri dianalogikan sebagai pengejawantahan The Divine menjadi bentuk material, sehingga karakteristik inheren dari yang-universal ini juga muncul dalam yang-partikular.
Karakteristik “one” atau satu atau tunggal disinyalir punya benang merah dengan konsep unity Plato. Bila menilik kembali pembahasan di bagian sebelumnya, The Divine yang mengejawantah dalam bentuk-bentuk material di dunia ini setara dengan pemosisian form dan idea oleh Plato. Aquinas percaya bahwa Tuhan dan seluruh makhluk terikat dalam satu kesatuan. Kesatuan inilah yang memegang kendali atas berjalannya semesta dan seisinya. Oleh karena itu, “one” merupakan karakteristik yang melekat pada pribadi Tuhan dan juga seluruh makhluk ciptaan.
Karakteristik yang kedua, “true” juga dipercaya Aquinas menjadi sifat dasar dari semua makhluk. Sifat “true” ini—sebagaimana sifat sebelumnya yang juga dibagikan dari The Divine—tidak diukur atau dicerna berdasarkan kecakapan intelektual manusia. Aquinas menyatakan bahwa, “even if the human intellect did not exist, things would still be said to be true in their relation to the divine intellect.”[2] Ringkasnya, sifat mengandung kebenaran ini tidak berkaitan dengan persepsi manusia untuk mengenali “kebenaran” itu benar adanya atau tidak, melainkan sudah jadi bawaan yang tetap eksis bahkan tanpa keberadaan intelektualitas untuk mengenalinya.
Pada karakteristik yang terakhir, “beauty” atau “good”, ada banyak kemiripan dengan filsafat estetika Plato. Aquinas menunjukkan bahwa “dari sananya”, semua makhluk ciptaan itu indah, sebab yang menciptakannya juga indah. “… [c]reated beauty is nothing other than a likeness of the divine beauty participated in things.”[3] Bedanya, Aquinas ternyata membedakan antara good dan beauty; penilaian atas kadar good adalah perkara selera, sementara beauty baru dapat dikenali ketika seseorang menggunakan kemampuan kognitifnya.
Ketiga karakteristik di atas melekat sebagai sifat dasar makhluk ciptaan (termasuk manusia). Kira-kira, dari sinilah kita mulai bisa mengenali bagaimana konsep estetika Aquinas dibangun. Keindahan yang ada dalam dunia material berasal dari sumber yang tunggal (the divine) dan sifat indah tersebut lahir dari kesatuan antara ciptaan dan penciptanya (objek dan senimannya). Karena keindahan material ini lahir sebagai “pengejawantahan” keindahan yang divine, maka objek tersebut indah pada dirinya sendiri. Persepsi manusia berfungsi untuk memahaminya dengan cara tertentu (yang akan saya jelaskan di bagian selanjutnya). Singkatnya, satu-satunya cara mengenali keindahan material tersebut adalah dengan menautkannya pada keindahan yang agung (divine) atau bisa kita sebut dengan: membaca keindahan secara alegoris.
Alegori Menjadi Jalan
Alegori bukanlah konsep yang terbilang baru. Secara khusus dalam tradisi biblikal Kristen, alegori diperkenalkan sebagai jalan untuk menemukan dan memahami makna-makna figuratif dalam teks kitab suci. Rumus membaca kitab suci dengan mengenali mana makna harfiah dan mana makna figuratif ini disusun oleh St. Agustinus dalam De Doctrina Christiana delapan abad sebelumnya. Aquinas melanjutkan teori tanda Agustinus—masih dalam rangka kepentingan membaca kitab suci—dengan merumuskan empat tingkatan makna.
Aquinas mendefinisikan alegori sebagai perpindahan dari penandaan benda menjadi penandaan kata. Proses perpindahan penandaan ini dilalui dalam empat tingkatan makna. Tingkatan makna versi Aquinas adalah sebagai berikut: literal, alegoris, moral, dan anagogis.[4] Dalam konteks kitab suci, makna literal merupakan lapisan yang menceritakan peristiwa. Makna alegoris adalah lapisan yang menautkan makna pada teks yang dibaca dengan makna yang ada di luar teks atau di dalam teks lain. Tingkatan moral merupakan pengolahan makna lebih jauh untuk mengenali apa yang dipesankan oleh teks itu untuk dilakukan pembaca. Sementara tingkatan anagogis menghadirkan makna yang memberi petunjuk tentang The Divine atau sesuatu yang transendental yang menjadi tujuan akhir manusia.
Secara sekilas, pembagian tingkatan ini memang semata-mata terkait kepentingan membaca kitab suci religius saja. Akan tetapi, Umberto Eco mencoba menjembatani upaya Aquinas membagi lapisan-lapisan makna ini dengan kontribusi teori tersebut dalam sastra. Serupa Plato, Aquinas menempatkan sastra di posisi yang lebih rendah ketimbang kitab suci mengingat teks sastra mengandung lebih sedikit kebenaran dibanding teks kitab suci. Akibatnya, hal-hal yang dimuat dalam teks sastra adalah objek yang hanya dibayangkan atau ditemukan, alias tidak nyata. Jika dikaitkan dengan karakteristik inheren transendental pada diri ciptaan, tentulah sastra tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki karakteristik “true” yang memadai. Akan tetapi, Eco melihatnya bukan sebagai penghinaan terhadap sastra, melainkan sekadar upaya Aquinas untuk menunjukkan bahwa ada hierarki pengetahuan.
Oleh karena sastra membicarakan hal-hal yang “tidak riil” alias dibayangkan saja itu, sastra harus menggunakan peranti metafora pada ekspresi verbalnya. Lalu, apa bedanya dengan metafora yang juga digunakan dalam teks-teks kitab suci? Umberto Eco menjelaskan bahwa teks kitab suci mengandung “misteri” yang melampaui kapasitas pemahaman manusia, sehingga harus diekspresikan dengan metafora dan alegori. Sementara sastra—yang dalam hierarki pengetahuan versi Aquinas berada di posisi lebih rendah ketimbang kitab suci—justru perlu menggunakan metafora dan alegori karena “kekurangannya” dalam hal pengetahuan akan kebenaran. Atau barangkali bisa kita bayangkan bahwa penulis sastra—yang hanyalah manusia biasa dengan keterbatasannya itu—tidak mampu mencapai makna spiritual teks kitab suci, sehingga harus mewakilkannya pada penanda-penanda lain dengan referen yang dapat kita kenali jelas bentuknya.
Dari dua pemikir yang melanjutkan perjuangan mengembangkan teori tanda yang pernah saya tulis dalam rangkaian terbitan ini—Agustinus dan Aquinas, dapat kita lihat bagaimana rumusan yang mereka buat menginisiasi pendekatan karya sastra dalam pencarian makna yang tidak berhenti pada teks saja. Ada lapisan-lapisan makna lain yang dapat ditelusuri dengan tetap berpijak pada teks tertentu yang dibaca. Pemikiran Aquinas, selayaknya sebagian besar pemikiran rekan sezamannya, memang tampaknya seperti “apa-apa Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan”. Akan tetapi, peran tradisi biblikal religius dari mereka ini turut menyumbangkan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu gramatika. Dalam tulisan Wahmuji, gramatika dikenali sebagai tulang punggung dalam budaya literasi yang “… tidak hanya dibangun dengan kemampuan memahami makna harfiah dari kata-kata, tetapi kemampuan mencari dan mencipta makna tersirat.” Aquinas dan tokoh skolastik lainnya yang mencari jalan untuk memahami kitab suci, ternyata melakukan upaya yang sekaligus membukakan lintasan untuk berkembangnya teori tanda dan pemaknaan atas teks yang melampaui makna literal.
Apa yang hingga kini kita kerap temui (dan kadang terbilang malah mandek di sana) dalam pembicaraan tentang karya, semacam pesan moral, makna dari karya, intensi pengarang, dst., ternyata telah diantisipasi dan dibicarakan oleh para pemikir Abad Pertengahan. Dari kebutuhan memahami yang “lain” atau yang “di luar teks” dalam tradisi kitab suci inilah, alegori yang menjadi salah satu peranti sastrawi yang kita kenal sekarang tumbuh dan menemukan peran signifikannya. Penautan makna secara alegoris pada hal-hal yang transendental banyak kita temui pada pembacaan religius atas teks. Sementara, pendekatan yang serupa sering pula digunakan dengan menautkan lapisan makna kedua (atau ketiga, dst.) pada dimensi lain, seperti moral, kemanusiaan, politik, dll.
[1] “Doktor” dalam konteks ini adalah gelar kehormatan spesifik dari institusi Gereja Katolik yang diberikan pada orang-orang yang dianggap memberikan kontribusi penting dalam doktrin dan teologi Kekristenan. Dalam lingkaran liturgis Gereja Katolik di Indonesia, gelar “Doktor” ini lebih dikenal dengan istilah “Pujangga Gereja”.
[2] Lihat Habib, 2005: 207.
[3] Lihat Habib, 2005: 208.
[4] Lihat Habib, 2005: 209. Kerangka ini juga diadopsi dan dijabarkan dalam pemikiran Dante Alighieri dalam konteks upayanya mempromosikan penggunaan bahasa vernakular untuk penulisan sastra.


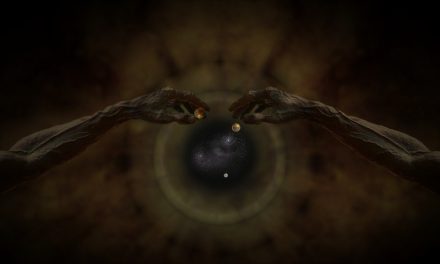



Komentar Terbaru