Gramatika atau tata bahasa dalam bahasa Indonesia bermakna sama dengan grammar; sedangkan kata sastra kita gunakan untuk mengacu pada literature dalam bahasa Inggris. Gramatika dan sastra sudah cukup lama berpisah dan menempati disiplin keilmuan berbeda, meski sering berada di dalam satu fakultas. Tata bahasa menginduk pada linguistik atau ilmu bahasa, sedangkan sastra menjadi disiplin yang mandiri. Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kata bahasa Latin litteratura, yang dalam bahasa Inggris menjadi literature, merupakan terjemahan dari bahasa Yunani grammatike. Dan kata litteratus mengacu pada orang yang paham tata bahasa dan puisi/sastra; orang yang telah banyak belajar; orang yang terdidik secara liberal [baca: bukan teologi].
Abad Pertengahan adalah masa ketika gramatika, dalam artian di atas, mengalami masa keemasannya—masuk dalam ‘trivium’ [gramatika, logika, retorika]. Kalau di masa Romawi retorika dianggap induk dan puncak ilmu pengetahuan, di Abad Pertengahan gramatika menggantikan posisi retorika sebelum kemudian digeser oleh logika. Singkatnya, gramatika merupakan ilmu tentang panduan membaca dan menulis, dan sekaligus tentang interpretasi karya sastra. Dalam kaitannya dengan kritik sastra, bagaimana corak gramatika di masa ini, apa bentuknya, dan apa yang bisa kita ambil sebagai warisan berharga? Untuk menjawabnya, akan dipaparkan hubungan gramatika dan sastra, dan secara ringkas pemikiran dari dua ahli dan pembela gramatika: Hugo dari St. Victor dan John dari Salisbury.
Gramatika dan Sastra
Budaya Abad Pertengahan disandarkan pada otoritas teks kanon, baik Pagan maupun Kristiani, meski hampir selalu berakhir pada Injil sebagai puncaknya. Sebagian besar aliran intelektual Abad Pertengahan dibangun dari tradisi penafsiran tekstual dari tradisi ‘gramatika’ klasik, yang dilanjutkan oleh para sarjana Kristiani untuk menafsir teks Injil. Gramatika-lah yang memungkinkan artikulasi dari otoritas teks, dan pada gilirannya juga menerima otoritas dari fungsinya.
Secara umum, ada empat dimensi interpretatif dari praktik gramatika. Lectio, atau membaca, adalah prinsip-prinsip ilmu persajakan dan membaca lantang (di depan publik); enarratio, atau eksposisi, merupakan penjelasan isi dan prinsip interpretasi; emendatio, atau koreksi, adalah aturan mengenai ketepatan linguistik dan autentisitas tekstual; dan iucidium, atau penilaian, merupakan kritik atau evaluasi atas teks.[i] Dari empat dimensi ini saja, kita sudah langsung bisa melihat luasnya cakupan praktik gramatika.
Dalam kaitannya dengan kritik sastra, meski interpretasi atas sebuah karya cenderung berfokus pada teks, bukan berarti pengarang tidak penting, bukan berarti makna puncak ada di dalam teks dan ditemukan oleh pembaca. Pengarang tidak “dibunuh” dan pembaca tidak sedang “dilahirkan”. Tradisi gramatika Abad Pertengahan sangat menekankan pentingnya pengarang, terutama dari masa klasik. Penghargaan terhadap (pengarang) karya klasik muncul dalam tiga tipe risalah. Pertama, komentar atas karya klasik; kedua, ars metrica atau teknik prosodi; dan ketiga, accessus atau prolog yang diberikan untuk karya dari pengarang klasik yang diterjemahkan.
Komentar atas karya klasik biasanya muncul dalam dan berbaur dengan teks karya klasik itu sendiri. Di masa itu, halaman-halaman untuk tulisan yang dicetak memiliki marjin yang sangat lebar, sehingga pada ruang itulah komentar dimasukkan oleh penulis. Tidak seperti di masa modern, teks ‘asli’ dan komentar juga agak sulit dipisahkan. Dalam gramatika, ars metrica diajarkan sebagai bagian penting untuk menginterpretasi teks sastra, khususnya puisi. Tentu saja puisi yang dipelajari dan diajarkan dalam kurikulum ‘trivium’ masa itu adalah puisi yang dianggap kanon, yang dilahirkan oleh distinguished authors. Biasanya, karya para distinguished authors diterjemahkan dan diberi prolog. Pengarang yang karyanya diterjemahkan berarti dianggap memiliki otoritas dan masuk kanon; dan pemberi prolog adalah orang yang mampu memahaminya, serta akhirnya memiliki otoritas untuk mencoba membangun sesuatu yang baru. Hubungan gramatika dan otoritas Injil juga terbangun dengan cara ini.
Karena bertumpu pada teks (kanon), maka gramatika juga memproduksi intertekstualitas: bahwa sebuah tulisan atau karya selalu diposisikan dalam perpustakaan teks yang lebih luas. Lebih jauh lagi, mengacu pada penelusuran Irvine, seperti dipaparkan Habib, di masa itu gramatika punya kecenderungan untuk ‘menggantikan dunia benda dengan dunia tanda’.[ii] Tentu saja klaim ini bisa kita perdebatkan, tetapi setidaknya, sejauh paparan singkat di atas, kita bisa melihat hubungan erat antara karya kanon, tradisi, pengarang baru, otoritas teks, dan pentingnya teknik dalam penulisan.
Hugo dari St. Victor
Tidak diketahui kapan dan di mana tepatnya Hugo dari St. Victor dilahirkan. Diperkirakan, ia lahir pada tahun 1096 dan meninggal pada tahun 1141. Hugo masuk Priory of St. Pancras, sebuah canons regular, yang terletak di Hamerleve, dekat Halberstadt. Tidak lama setelah ia masuk Priory, terjadi kerusuhan dan atas nasihat pamannya, ia pindah ke Abbey of Saint Victor di Paris, tempatnya belajar teologi. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana, mengajar dan menjadi kepala sekolah.
Hugo dari St. Victor dikenal sebagai mistikus Kristiani dan sangat terpengaruh oleh St. Agustinus, terutama kepercayaannya bahwa filsafat dan seni bisa melayani teologi. Kepercayaan itu khas Abad Pertengahan, dan merupakan upaya untuk merekonsiliasi budaya/tradisi Pagan dan Kristiani. Karya utama Hugo yang berkaitan dengan sastra adalah Didascalicon (kata Yunani yang berarti instruktif atau cocok untuk jadi bahan ajar). Didascalicon fokus pada membaca, dalam arti membangun pedoman mengenai apa yang harus orang baca, serta tatanan dan cara membaca, baik untuk seni maupun kitab suci.
Seperti umumnya para pemikir Abad Pertengahan, jalan awal yang ditempuh Hugo untuk mempresentasikan pikirannya adalah dengan membangun sendiri hierarki keilmuan dan mendefinisikan ulang jenis-jenis ilmu. Namun, seperti juga pemikir lainnya, Hugo mengakui pentingnya kurikulum pendidikan yang disebutnya sebagai “tujuh seni liberal” [trivium dan quadrivium]—kata seni di sini bermakna disiplin pengetahuan. Quadrivium terdiri dari aritmatika, musik, geometri, dan astronomi; sedangkan trivium meliputi gramatika (tata bahasa), dialektika/logika, dan retorika. Hugo mendefinisikan gramatika sebagai “pengetahuan untuk berbicara tanpa kesalahan”, dialektika sebagai “argumen tajam” yang memisahkan kebenaran dan ketidakbenaran, dan retorika “disiplin untuk meyakinkan”.
Definisi gramatika ala Hugo di atas kini mungkin tampak preskriptif dan mengafirmasi ejekan terhadap kalangan tata-bahasawan (dan penerjemah!) yang sangat mementingkan kebenaran penulisan ejaan, penggunaan kata dan tanda baca, dan penyusunan kalimat. Namun, dalam konteks pendidikan, Didascalion karya Hugo sangatlah berguna. Dan, seperti saya sebut di awal, Hugo sebenarnya cenderung fokus pada apa yang mungkin sekarang disebut sebagai ‘pendidikan literasi’—pendidikan untuk meningkatkan kemampuan membaca.
Saat kita menguraikan sebuah teks, kata Hugo, penjelasan kita meliputi tiga unsur: huruf (letter), pengertian (sense), dan makna mendalam (inner meaning). Huruf adalah susunan kata-kata yang berkesinambungan; pengertian merupakan makna yang sudah jelas, yang permukaan, yang dihadirkan oleh susunan kata-kata; sedangkan makna mendalam, sesuai sebutannya, hanya bisa ditemukan melalui interpretasi dan komentar. Penjelasan kita berjalan berurutan sesuai ketiga unsur itu, dari yang sudah jelas ke arah yang belum terdefinisikan. Cara membaca seperti ini tidak asing bagi kita sekarang [denotasi & konotasi; makna tingkat pertama & makna tingkat kedua], dan hakikatnya tidak berubah selama lebih dari 900 tahun!
Skema serupa diajukan Hugo untuk membaca Kitab Suci. Menurut Hugo, Kitab Suci punya tiga cara untuk menyampaikan makna, yaitu sejarah (history), alegori (allegory), dan tropologi (tropology). Sejarah, dalam bentuk cerita, merupakan tingkat harfiah dari makna. Cerita Kitab Suci merupakan sarana bagi kita untuk mengagumi apa yang telah dilakukan Tuhan. Namun, karena masih berupa makna harfiah, sejarah Kitab Suci penuh dengan ketidakjelasan, kontradiksi, dan ketidakmungkinan. Karena itulah, pengertian mistis atau spiritual dibutuhkan. Di level pemaknaan ini, tidak ada lagi oposisi, tidak ada lagi kontradiksi; yang ada hanya perbedaan. Melalui pemaknaan spiritual, kita diajak untuk “mempercayai misteri-Nya”. Terakhir, tropologi, merupakan penafsiran moral. Dengan penafsiran jenis ini, kita berusaha untuk meniru kesempurnaan Tuhan.
Sejarah, dalam pengertian di atas, dianggap Hugo sebagai fondasi penting, makna pertama, yang darinya kebenaran alegoris bisa disarikan. Tanpa pemahaman sejarah, kita tidak akan mampu sampai pada kebenaran alegoris. Dengan kata lain, tanpa pemahaman atas kata-kata, atas struktur cerita, atas makna harfiah dari teks Kitab Suci, kita tidak mungkin bisa beranjak ke tingkat makna selanjutnya, yang spiritualis, sebuah ruang makna harmonis tanpa kontradiksi. Pun begitu, Hugo tidak mengharuskan kita untuk mencari ketiga jenis makna di atas sekaligus ketika membaca Kitab Suci. Kita mesti mengandalkan nalar kita untuk memilih jenis makna mana yang paling tepat untuk kondisi spesifik.
Sebagian dari kondisi beragama di Indonesia sekarang, seperti maraknya ‘lomba’ kutipan, meningkatnya penggunaan arti harfiah dari kata-kata yang tertera di Kitab Suci untuk dijadikan acuan akhir dalam praktik agama, dan tekanan moral yang berlebihan pada praktik hidup sehari-hari, bisa dibaca sebagai dominasi pembacaan ‘sejarah’ dan pembacaan ‘tropologis’ dalam pengertian Hugo. Karena dominasi itu, tidak muncul aura mistis dan spiritualis dalam beragama, tidak ada kedamaian tanpa kontradiksi, dan Tuhan kehilangan sisi misterius-Nya. Yang hadir hanyalah kekakuan makna harfiah dan moralitas yang disandarkan melulu pada makna harfiah itu.
Filsafat dan Kitab Suci, di mata Hugo dan secara umum di Abad Pertengahan, dianggap beda tingkat dan karenanya mesti dibaca dengan setelan standar yang berbeda. Seorang filsuf, kata Hugo, hanya tahu makna kata yang dibangun dari konvensi dan mengekspresikan suara manusia. Sedangkan makna benda-benda, yang didikte oleh alam, mengekspresikan suara Tuhan [yang lebih tinggi dari suara manusia]. Kata adalah “tanda dari persepsi manusia” sedangkan benda merupakan “tiruan dari ide ilahiah”. Suara manusia bersifat eksternal dan sementara, sedangkan suara Tuhan bersifat internal dan abadi. Tulisan filsuf mencampur-adukkan kebenaran dan ketidakbenaran, sedangkan Kitab Suci membawa kebenaran absolut dan bebas dari ketidakbenaran. Ini karena Kitab Suci diproduksi oleh orang yang dididik dengan kepercayaan Katolik dan telah mendapat persetujuan “otoritas dari gereja yang universal”.
Sama seperti pandangan mengenai level makna, pemikiran Hugo dari St. Victor mengenai perbedaan tingkat antara Kitab Suci dan non-Kitab Suci serta sikap dasar dalam memperlakukan keduanya juga bertahan lama, bahkan hingga kini. Meski kadang terasa ‘ujung-ujungnya Tuhan’, paparan Hugo mengenai beragam cara pemaknaan, pentingnya pemahaman terhadap makna harfiah sebagai fondasi makna-makna selanjutnya, perhatiannya pada pendidikan membaca, dan secara umum usahanya untuk bergulat dengan bahasa, memberi kontribusi besar pada tradisi literasi, pada budaya yang berbasis teks, pada sastra yang percaya pada kemampuan kata-kata.
John dari Salisbury
John dari Salisbury lahir antara tahun 1115 dan 1120 di Old Sarum, dekat tempat yang sekarang disebut Salisbury, Inggris. John belajar logika dan gramatika di Perancis pada orang-orang tersohor di masa itu. Ia menghabiskan hidupnya dengan menempati posisi-posisi penting dalam gereja, dan pada tahun 1176, ia ditunjuk menjadi uskup Cartres dan menjabat sampai ajal menjemputnya pada tahun 1180.
Karya utama John dari Salisbury adalah Policratius & Metalogicon. Policratius adalah buku pedoman untuk pejabat, sedangkan Metalogicon adalah buku pembelaan atas trivium. Dalam Metalogicon, John ‘mencipta’ seorang musuh dengan pseudo-nama Cornificius. Menurutnya, Cornificius dan para pengikutnya menganggap bahwa kemampuan retoris dan kecerdasan intelektual merupakan anugerah alamiah; dan pelajaran bahasa dan logika tidak membantu orang memahami dunia. Kaum Cornifician ini, yaitu pendeta, dokter, pengacara, dan penggila uang, juga menganggap kebijaksanaan berbanding lurus dengan kemulusan karier.
John menyatakan bahwa logika (dalam arti luas, termasuk gramatika) tidak bisa dipelajari secara terisolasi, dan merupakan wahana penting guna memupuk eloquence atau ekspresi yang anggun, persuasif, dan menggerakkan. Meski secara umum membela trivium dan menggunakan logika sebagai istilah umumnya, John sebenarnya lebih banyak membahas gramatika.
Bagi John, gramatika adalah “ilmu berbicara dan menulis dengan benar – titik berangkat semua kajian liberal”[iii]. Gramatika tidak hanya mencakup studi tentang sifat dan makna huruf, suku kata dan kata-kata, tetapi juga prosodi, aturan puisi, definisi dan penggunaan majas, dan metode yang digunakan dalam narasi fiksi dan sejarah. Lebih jauh, menurutnya filsafat dibentuk secara internal oleh sifat dan jangkauan bahasa yang tunduk pada hukum gramatika.
Salah satu fungsi utama gramatika adalah sebagai tempat lahir semua filsafat. Gramatika “merawat kita sewaktu bayi, dan menuntun kita di setiap langkah filsafat yang kita ambil”[iv]. Dengan kata lain, gramatika merawat seorang filsuf dari awal hingga akhir pencariannya. Ia menyiapkan pikiran untuk memahami segala hal yang bisa diajarkan dalam kata-kata. Semua kajian lain, kata John, bergantung pada gramatika.
Selain sebagai tempat lahir filsafat, gramatika juga disebutnya sebagai perawat pertama dari seluruh kajian sastra. Ia adalah ibu dan wasit dari semua tuturan. Berbeda dari bahasawan modern Ferdinand de Saussure, John menganggap bahwa penanda bukanlah tuturan, melainkan kata, apa yang tertulis. Dari para penulis akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama karena pengaruh kuat Romantisisme, kita memahami sastra sebagai (medan) otonom. Akan tetapi, dari perspektif Abad Pertengahan, termasuk dalam pandangan John, sastra ditempatkan di bawah gramatika. Karena itulah, sastra dianggap tunduk pada aturan-aturan, pada benar dan salah. Penyimpangan dari aturan gramatika sangat mungkin terjadi, tetapi penyimpangan itu pun akan (di)sesuai(kan) dengan prasyarat atau aturan yang sudah ada.
‘Aturan,’ dalam penjabaran John, selain bisa dipahami secara intrinsik, juga bisa diperluas di level ‘tradisi’. Setiap orang, kata John, akan mencoba membetulkan kesalahan tertentu dari para pendahulunya saat ia sedang mengukir nama untuk dirinya sendiri (melalui tulisan). Di saat yang sama, dalam upayanya untuk membetulkan, ia juga menjadi target dari koreksi dan ketidaksetujuan dari generasi setelahnya. John juga menempatkan dirinya dalam skema ‘anxiety of influence’ itu dengan mengatakan bahwa “the same rule threatens to apply in my own case”.[v]
Ringkasnya, analisis ala John dari Salisbury bisa dirangkum ke dalam tiga prinsip. Pertama, kualitas yang paling diinginkan dalam sebuah tulisan adalah “lucid clarity and easy comprehensibility”. Kata-kata adalah media untuk ‘berhubungan intim’ dengan realitas atau dunia objek sehingga rangkaian kata-kata mesti jelas dan mudah dipahami. Kedua, imitasi pengarang besar. Imitasi dalam wacana tekstual di Abad Pertengahan cenderung tidak mengacu pada peniruan atas dunia objek, tetapi atas tulisan pengarang sebelumnya. Aturan dan tradisi, seperti diungkap sebelumnya, sangatlah penting di masa ini. Seorang sastrawan dan karyanya tidak mungkin bermakna tanpa latar aturan dan tradisi yang ada. Ketiga, maksud pengarang selalu dilestarikan. Untuk dapat memahami maksud pengarang, kita mesti bersikap simpatik, dan kita memerlukan pemahaman harfiah sekaligus makna tersiratnya.
Gramatika juga memiliki peran yang penting terkait dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Menurut John, pengetahuan kita atas dunia material berawal dari indra. Imajinasi bekerja mengolah data yang diterima oleh indra dan rasio menembus persepsi-indrawi untuk membawa kita pada perenungan. Kecakapan tertinggi kita sebagai manusia adalah semacam pengetahuan intuitif yang menuntun kita mencapai kebijaksanaan spiritual. Sedangkan kebajikan, kata John, harus dibangun dari pengetahuan. Karena gramatika adalah akar dari pengetahuan ilmiah, maka gramatika-lah yang mula-mula menanamkan kebajikan.
Gramatika dan Budaya Literasi
Ada banyak upaya, yang telah dan sedang dilakukan oleh negara maupun secara mandiri oleh banyak lembaga dan komunitas, untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan kemampuan menulis, membangun budaya literasi. Dengan nada prihatin, tetapi sekaligus sebagai dasar gerakan, kita sering membandingkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia dengan tingginya minat baca “Orang Barat”. Saya sepakat dengan perbandingan semacam itu, asal tidak heroik dan berlebihan.
Kalau kita memakai tradisi-baca Eropa sebagai cermin bagi budaya literasi kita dan menganggap budaya literasi mampu memberikan dampak yang baik bagi upaya manusia memahami dunia, saya rasa tradisi pendidikan Abad Pertengahan Eropa, dengan salah satu penekanannya pada gramatika, patut kita pertimbangkan sebagai referensi. Pemberantasan buta huruf mungkin sudah berhasil, tetapi peningkatan kemampuan membaca (dan menulis), baik sastra maupun teks-teks lainnya, merupakan persoalan berbeda. Budaya literasi tidak hanya dibangun dengan kemampuan memahami makna harfiah dari kata-kata, tetapi kemampuan mencari dan mencipta makna tersirat.
Definisi gramatika di Abad Pertengahan dan sistem pengetahuan yang coba dibangunnya tidak hanya memberikan beberapa warisan berharga dalam kritik sastra—tingkat-tingkat makna, tradisi dan kebaruan, aturan dan penyimpangan, dll.—tetapi juga literasi secara umum: bahasa adalah ibu dan perawat setia saat kita bergulat memahami dunia.
[i] Ars Victorini dalam M.A.R. Habib, A History of Literary Criticism: From Plato to the Present, hal. 177.
[ii] M.A.R. Habib, A History of Literary Criticism: From Plato to the Present, hal. 178.
[iii] Idem, hal. 185
[iv] Idem, hal. 185
[v] Idem, hal. 188

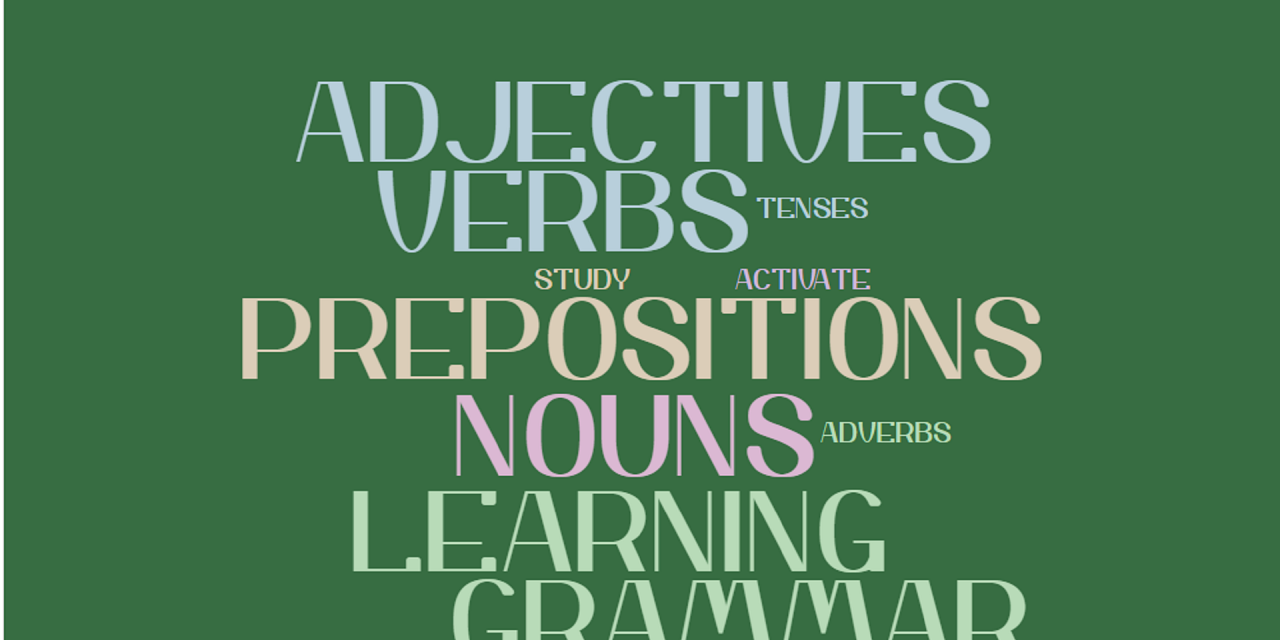




Trackbacks / Pingbacks