Istilah ancient dalam ancient literature atau ancient literary criticism mengacu pada rentang masa yang cukup panjang, setidaknya dari Plato (429-347 SM) hingga ‘Servius’ (abad ke-4 Masehi) atau bahkan Santo Agustinus (354-430 M). Rentang masa itu masih bisa diperpanjang lagi kalau kita lihat bahwa salah satu karya yang banyak dibahas Plato sampai para pemikir Romawi adalah karya Homer, seorang pengarang yang hidup di abad ke-8 Sebelum Masehi. Di Barat, kritik sastra kuno ([KSK]—Ancient Literary Criticism) sudah menjadi spesialisasi akademis tersendiri dan para ahlinya biasa disebut classicist—makanya kadang-kadang ancient juga disebut classic meski istilah classic bisa juga mengacu pada karya-karya terpilih di luar rentang masa kuno. Namun, KSK bukan hanya dipelajari oleh mereka. Sudah umum dipahami, setidaknya di Barat, bahwa KSK merupakan material yang dianggap penting untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai kritik sastra sebagai sebuah displin keilmuan tersendiri, sebuah disiplin yang sudah berumur sangat panjang.
Dalam praktiknya, para classicist dan ‘kritikus sastra kontemporer’ memiliki corak yang berbeda dalam memperlakukan KSK. Mengutip kesimpulan panjang Andrew Laird, “modern literary and cultural theory, in so far as it bears on poetics, has been cosmopolitanizing and promoting ancient literary criticism while classicists have been more concerned with establishing the context of critical production in antiquity.”[i] Dengan kata lain, perilaku kritikus sastra kontemporer mengarah pada promosi KSK sebagai sesuatu yang berharga, sedangkan classicist berusaha mengonstruksi keunikan masa lalu. Bagaimanapun, kedua posisi itu menghadapi sebuah persoalan yang sama, yakni bagaimana kita, orang-orang modern (dan mungkin bahkan pascamodern!) membaca dan memahami KSK. Semua menghadapi persoalan historiografi yang sama.
Persoalan historiografi itu perlu dibahas apabila kita hendak mengambil ‘nilai’ dari KSK untuk kita hari ini—sesuatu yang hendak dicari dalam tulisan ini. Selain historiografi, kita juga perlu memahami, paling tidak secara garis besar, corak kritik sastra kontemporer untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang bisa dikontribusikan oleh KSK. Dan terkait dengan keduanya, kita sendiri juga perlu merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan secara personal dari memelajari KSK.[ii] Dari yang-personal inilah justru arti dari memelajari KSK terasa lebih nyata dan dalam.
Persoalan Historiografi
Dalam persoalan historiografi, kita berhadapan dengan dilema memandang masa lalu secara sinkronik atau diakronik. Keduanya membawa keuntungan dan jebakan sendiri-sendiri. Cara pandang diakronik memampukan kita melihat secara kronologis perkembangan-perkembangan definisi, konsep, dan fokus dari sejarah kritik sastra secara umum, dari KSK hingga modern, maupun kritik sastra kuno itu sendiri, yang jangka waktunya sangat panjang. Jebakan dari cara pandang diakronis adalah apa yang disebut sebagai ‘narasi teleologis’, bahwa kritik sastra berkembang secara alamiah dan lebih jauh lagi arahnya sudah jelas. Jadi, perkembangan kritik sastra kuno dilihat sebagai self-realization dari kritik sastra kontemporer. KSK dilihat sebagai pembenaran dari kritik sastra modern. Di sisi lain, cara pandang sinkronik memampukan kita melihat kritik sastra kuno sebagai sebuah sistem yang bisa digambarkan cara kerjanya. Dengan demikian, kita bisa memeriksa corak kritik sastra kuno untuk ‘dibandingkan’ dengan kritik sastra kontemporer. Namun, jebakan yang mungkin hadir adalah perbandingan itu dilakukan tanpa konteks sejarah (sosio-politik) yang secara eksplisit dihadirkan. Paradoksnya, dengan menghadirkan konteks sosial-politik, kita mungkin tidak punya ruang sama sekali untuk membuat sebuah perbandingan (kondisinya kan sudah jelas berbeda!).
Persoalan historiografi lainnya, dalam konteks spesifik KSK, adalah pertanyaan ini: sejauh mana kita bisa mengonstruksi masa lalu dalam istilah-istilah dan konsep-konsep dari masa itu sendiri? Pertanyaan ini mengemuka karena beberapa sejarawan KSK terpenting, seperti Malcom Health dan Cairn, bahkan buku yang punya prestise tinggi, The Cambridge History of Literary Criticism, berusaha untuk ‘seobjektif’ mungkin melihat KSK. Dalam pengantar untuk The Cambridge History of Literary Criticism, dinyatakan bahwa para penulisnya “have thought it best to expound the ancient critics in [those critics’] own terms rather than to recast their thought in alien concepts.”[iii] Keengganan untuk memasukkan ‘konsep-konsep alien’ dalam pembicaraan mengenai masa lalu seperti itu mungkin terlihat lebih adil, lebih tidak menghakimi, tetapi di saat bersamaan menghadirkan persoalan yang pelik: apakah kita memang bisa berbicara dengan ‘bahasa’ di luar zaman kita? Klaim bahwa kita mampu untuk berpikir dan berbicara dengan cara-pikir dan konsep-konsep zaman tertentu telah mendapatkan banyak kritik. Dalam diskusi kali ini saya akan mengambil kritik dari esai Andrew Laird “The Value of Ancient Literary Criticism” dan Denis Feeney “Criticism Ancient and Modern.”[iv]
Dalam konteks sastra, kita baru mendapatkan kategori matang mengenai ‘sastra’ (literature) setelah Pencerahan. Dalam frasa ancient literary criticism sendiri, yang mengandung kata literary dan mengacu pada literature, sudah muncul konsep alien atau asing. Ancient mengacu pada rentang waktu sebelum Pencerahan, bahkan bisa dikatakan sebelum Pertengahan, atau paling jauh awal-awal Pertengahan. Sedangkan fitur makna ‘sastra’ yang kita bayangkan sekarang—seperti ‘berbentuk tulisan’, ‘berupa fiksi’, dan ‘dibagi dalam tiga genre puisi, prosa, dan drama’—tidak seperti makna yang diyakini oleh orang-orang Yunani dan Romawi antara abad ke-8 SM sampai abad 4 Masehi. Seperti dinyatakan oleh M.A.R. Habib, seorang kritikus sastra Inggris berdarah Pakistan, ‘sastra’ di masa Yunani mengacu pada hampir semua bentuk seni dan jurnalisme yang ada di masa ini.[v] Bahkan, makna genre yang kita pahami sekarang juga merupakan warisan Pencerahan.[vi]
Kedua, hasrat untuk memeriksa suatu zaman dalam kategori zaman yang diteliti adalah bagian dari positivisme abad ke-18 yang hasrat terbesarnya adalah mendapatkan hasil penelitian yang benar-benar objektif dan steril dari pengaruh peneliti. Objektivisme dari positivisme sudah banyak dikritik oleh para pemikir di masa setelahnya. Upaya untuk merekonstruksi kritik sastra kuno seakurat mungkin tanpa melibatkan subjektivitas merupakan praktik yang mengingkari kondisi sosial-politik dan wacana-wacananya yang membentuk cara berpikir seorang peneliti.
Terkait dengan persoalan objektivitas-subjektivitas ini, masalah ketiga dari rekonstruksi anti-konsep-alien adalah jebakannya pada narasi keantikan—sesuatu yang jadi arah beberapa classicist—seperti disinggung sebelumnya. Narasi ini sering menjebak kita pada klaim-klaim bahwa orang-orang di masa kuno telah jauh melampaui kita hari ini, bahwa merekalah satu-satunya jalan keluar bagi persoalan kritik sastra kontemporer.
Masalah terakhir adalah kenyataan bahwa dalam melakukan penelitian atas masa lalu, kita memilih bagian yang spesifik dan mengabaikan bagian yang lain. Artinya, kita sudah memakai sebuah konsep dan alur saat memilih data mana yang mau dipakai dan mana yang akan dibuang. Dengan demikian, kita tidak mungkin mengetahui masa lalu secara utuh dalam ‘bahasa’ mereka sendiri.
Karena klaim untuk tidak memakai konsep alien susah diterima, bagaimana selanjutnya kita membaca KSK? Mula-mula, kita musti menerima kenyataan bahwa kita memakai konsep-konsep asing dalam melihat kondisi spesifik di masa lalu. Reflektivitas ini penting. Justru dengan demikian kita secara sadar melihat masa lalu dari perspektif masa kini. Dan di saat bersamaan kita tahu batas-batas dari apa yang kita lakukan. Dari sanalah kita justru bisa memikirkan kondisi sekarang dan masa depan. Selanjutnya, dari kesadaran itulah, kritik sastra kuno bisa kita gunakan sebagai—mengutip Feeney—“bantuan, bahkan panduan, tetapi bukan resep atau pengekang.”[vii]
Corak Kritik Sastra Kontemporer
Salah satu persoalan yang dibahas para kritikus sastra dan budaya sejak paling tidak tahun 1960-an adalah perihal definisi sastra. Persoalan definisi ini mencuat karena munculnya pemikiran-pemikiran kritis (‘teori’—menurut istilah Peter Barry)[viii] yang mempertanyakan keabsahan definisi sastra dalam tradisi sastra yang ada. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, menurut Jonathan Culler, seorang profesor English and Comparative Literature di Universitas Cornell, tidaklah terkait dengan ketakukan bahwa orang mungkin akan kesusahan untuk membedakan, misalnya, karya sastra dengan iklan rokok. Persoalan definisi lebih terkait dengan fitur-fitur makna apa saja yang membuat sesuatu bisa disebut sebagai sastra dan makna macam apa yang mampu ditimbulkan oleh bentuk produk kultural yang dinamakan sastra. Sesuatu yang belum tereksplorasi oleh para kritikus sebelumnya.
Andrew Laird paling tidak menyebut dua fitur makna, yakni reuseable dan defamiliarization of language. Sebuah karya sastra bisa digunakan lagi dan lagi oleh pembaca (dalam bahasa yang agak esensialis: sebuah karya tetap punya nilai meski zamannya berbeda atau bahkan melampaui zamannya). Tapi, konsep reusability Andrew Laird ini melibatkan pembaca, bukan melulu teksnya. Maksudnya, reusability dipahami bukan dari ‘kebesaran’ sebuah karya saja, tetapi lebih fokus pada bagaimana orang-orang di masa yang lebih terkini memaknai ulang teks-teks dari masa sebelumnya. Pemaknaan-ulang terus-menerus inilah yang membuat sastra memiliki tradisi dan menjadikan teks sebagai sastra. Sedangkan defamiliarization of language mengacu pada cara penggunaan bahasa secara tidak lazim. Ketidaklaziman melalui permainan fitur-fitur linguistik inilah yang justru mendefinisikan sastra. Lebih luas dari Laird, Jonathan Culler menerangkan lima fitur makna yang mendefinisikan sastra: (a) sastra sebagai ‘pelatardepanan bahasa’, (b) sastra sebagai integrasi bahasa, (c) sastra sebagai fiksi, (d) sastra sebagai objek estetis, dan (e) sastra sebagai intertekstual atau bangunan refleksi-diri. Saya kira rincian atas lima fitur itu tidak perlu dijelaskan di sini. Yang terpenting dan terutama adalah bahwa definisi-definisi itu berfungsi untuk menjelaskan sastra sebagai ‘label institusional’ yang “memberi kita alasan untuk berharap bahwa hasil dari upaya pembacaan kita itu bernilai atau berharga.”[ix]
Persoalan, atau lebih tepatnya usaha untuk mempersoalkan, definisi sastra ini merupakan bagian penting dari orientasi kritik sastra di masa itu hingga sekarang. Dari problematisasi definisi sastra kita mendapatkan kerumitan baru. Persoalan kritik sastra menjadi lebih rumit dari definisi sastra karena istilah ‘kritik’ tidak dimaknai sebagai melulu ‘penghakiman’ atau ‘penilaian’ mengenai, misalnya, sejauh mana teks ditulis dengan defamiliarization of language tertentu atau bagaimana teks digunakan lagi—berarti juga dimaknai ulang—oleh para pembaca di masa berbeda. Kritik punya makna lebih luas, yakni persoalan jenis ‘nilai’ baik yang ada dalam sebuah karya maupun dalam ruang sosial yang menghasilkannya. Dengan kata lain, kritik sastra kontemporer punya kecenderungan untuk tidak hanya membahas sebuah teks sastra, tetapi seluruh semesta yang memungkinkan adanya sebuah karya sastra dan bagaimana ia diterima.
Andrew Laird menjabarkan skema kritik sastra kontemporer sebagai berikut:
- Representasional: Produksi sastra dapat dipahami dan dievaluasi dalam hubungannya dengan dunia atau realitas yang ia praandaikan, representasikan, atau konstruksi.
- Ekspresif: Produksi sastra dapat dipahami dan dievaluasi dalam hubungannya dengan ekspresi mengenai identitas, kepribadian, atau keadaan psikologis pengarangnya.
- Formal: Produksi sastra dapat dipahami dan dinilai dalam hubungannya dengan bentuk atau gaya.
- Pragmatik: Produksi sastra dapat dipahami dan dinilai dalam hubungannya dengan efek-efek yang ditimbulkannya (emosional, edukasional, sosial, dll.) terhadap pembaca atau
Skema yang dibuat oleh Andrew Laird itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjabaran M.H. Abrams, seorang kritikus yang terkenal dengan bukunya The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (1953). Buku itu, sejauh saya tahu, dipakai sebagai bahan ajar di banyak jurusan sastra di Indonesia. Pengaruh M.H. Abrams diakui sendiri oleh Andrew Laird, terutama pengaruh dari artikel M.H. Abrams, “Poetry, Theories of”. Bedanya, menurut Andrew Laird, Abrams lebih fokus pada emosi dan pleasure, sedangkan Laird lebih menekankan poros pragmatik. Perbedaan itu masuk akal mengingat fokus M.H. Abrams adalah masa Romantik. Dan yang terjadi sejak tahun 1960-an, kata Laird, adalah menguatnya poros pragmatik dalam kritik sastra. Bagi Laird, Practical Criticism dan New Criticism termasuk dalam poros pragmatik meski secara bersamaan mereka mendasarkan diri pada analisis formal teks. Ikut digolongkan Laird ke dalam poros itu antara lain kritik politis, religius, dan feminis. Belum lagi kalau kita bicara reader-response criticism yang nyata-nyata berbicara mengenai resepsi dan penerimaan pembaca.
Dalam praktik, kritik sastra sering kali menggunakan berbagai orientasi dalam skema di atas secara bersamaan. Namun, dalam setiap zaman kita melihat dominasi orientasi yang mungkin berbeda. Dengan memakai skema itu, Laird mencoba membuat topologi kritik sastra terkini dan selanjutnya melihat-ulang kritik sastra kuno. Dari sanalah nilai dari kritik sastra kuno coba dirumuskan.
Nilai Kritik Sastra Kuno
Menurut Laird, dibanding masa ini, KSK secara umum lebih menyeluruh dalam membahas keempat poros itu secara bersamaan. Namun, bukan berarti semua kritikus membahas semuanya. Poetics-nya Aristoteles, misalnya, yang fokus pada bentuk dalam representasi, tidak bisa “melarikan diri” dari pembicaraan mengenai fungsi pragmatis sastra (meski poros ekspresif jarang dibicarakan); sebaliknya, Longinus membahas formalitas teks dan pengarang, tetapi jarang peduli dengan aspek representasional dari sastra. Di masa terkini, fokus sebuah analisis cenderung lebih spesifik dan poros ekspresif jarang dibicarakan. Meski KSK cenderung menyeluruh dalam orientasi kritiknya, tetapi estetika dan gaya tetap merupakan evaluasi utama.
Dari perbedaan dalam orientasi itu, lalu apa yang bisa diambil dari kritik sastra kuno? Laird mengutip kata-kata terkenal dari T.S. Eliot untuk menjawab pertanyaan itu. “The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards,” kata Eliot. Tetapi, ia melanjutkan, “though we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standards.” Dalam pandangan Eliot itu kita melihat dua jenis legitimasi. Legitimasi pertama berdasarkan pencapaian literariness atau standar-standar sastra yang berguna untuk mendefinisikan dirinya sendiri (apa itu sastra) dan literary excellence atau pencapaian literer dalam sebuah karya. Sedangkanlegitimasi kedua berdasarkan ukuran-ukuran lain di luar literariness dan literary excellence (misalnya: tingkat subversifnya, visi dunianya, dll. yang terkait dengan, singkatnya, cara pandang atau ideologi baik pengarang, teks, atau suatu zaman). Melalui kutipan Eliot inilah Laird ingin mengatakan bahwa di tengah kuatnya orientasi pragmatik dalam kritik sastra kontemporer, kita diingatkan oleh KSK akan pentingnya estetika.
Saya kira jawaban Laird di atas bukan untuk membuat kita kembali pada estetika dan gaya (murni), tanpa mengindahkan politik dan ideologi. Akan tetapi, sebaliknya, melalui KSK, kita diajak untuk memahami lagi sebuah karya sastra sebagai ekspresi literer dari seorang pengarang yang bergulat dengan tradisi sastra yang ada maupun lingkungan sosialnya. Atau, dengan kata lain, sebuah karya sastra tetaplah sebuah karya individual meski ia merupakan produk budaya seperti juga produk-produk seni lainnya.
Selain ajakan untuk memberi perhatian pada estetika dan gaya, KSK memberitahu kita bahwa banyak konsep yang kini kita gunakan memiliki sejarah panjang. Di titik ini, KSK memampukan kita untuk menilai-ulang dan, kalau perlu, mengoreksi konsep-konsep terkini dari awal-mula dan penerimaan-penerimaannya sepanjang sejarah. Namun, kita baru bisa melakukan itu apabila tidak melihat kritik sastra secara apa adanya di masa itu tanpa konsep-konsep asing dari masa kini, melainkan justru kita mesti melihat KSK dengan apa yang kita punyai sekarang. Dengan demikian, kita merasakan betul potensi-potensinya.
Sebelum berpikir jauh mengenai penilaian-ulang dan pengoreksian, secara pribadi saya sangat terbantu dengan KSK dalam persoalan yang lebih mendasar. Saat memelajari kritik sastra maupun ilmu-ilmu sosial humaniora, saya merasa dijatuhkan di jalan raya wacana, dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berseliweran, saling menyalip, bahkan bertubrukan. Dan saya tidak tahu dari mana dan mau ke mana teori-teori dan konsep-konsep itu bergerak. KSK memberikan petunjuk untuk melihat asal dan arah dari berbagai konsep yang sebelumnya tampak berseliweran tak teratur itu. Bahkan kadang-kadang, saya harus jujur, saya merasa banyak orang di masa kuno yang telah melampaui kita.
___________________________
[i] Andrew Laird, “The Value of Ancient Literary Criticism”, dalam Oxford Readings in Ancient Literary Criticism, 2006, hal. 9.
[ii] Saya memasukkan persoalan makna personal ini karena bagaimanapun tulisan ini merupakan bagian dari serial Diskusi Sejarah Kritik Sastra yang dilakukan oleh sekelompok kecil peminat yang diorganisir Mediasastra.com (sekarang mediasastra.net).
[iii] Andrew Laird, “The Value of Ancient Literary Criticism”, dalam Oxford Readings in Ancient Literary Criticism, 2006, hal. 7.
[iv] Keduanya maktub dalam buku Oxford Readings in Ancient Literary Criticism.
[v] Lih. Modern Literary Criticism and Theory: From Plato to the Present, 2005.
[vi] Lih. “Ancient Literary Genres: A Mirage?” karya Thomas G. Rosenmeyer dalam Oxford Readings in Ancient Literary Criticism, 2006, hal. 421.
[vii] “Criticism Ancient and Modern”dalam Oxford Readings in Ancient Literary Criticism, 2006, hal. 441.
[viii] Lih. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory.
[ix] Lih. Literary Theory: A Very Short Introduction, 1997, hal. 9.


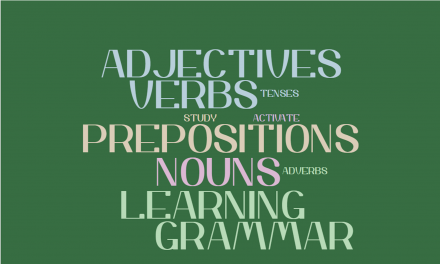


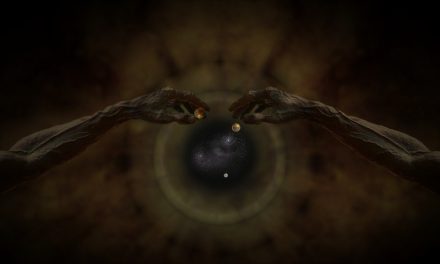
Komentar Terbaru