Harus diakui bahwa nama Horace tidak seterkenal Plato dan Aristotle. Kedua tokoh legendaris ini sama-sama mendirikan sekolah: Plato membuat Academy, sedangkan Aristotle mendirikan Lyceum. Saking legendarisnya, bahkan A.N Whitehead sebagaimana dikutip dalam buku Habib menyatakan filsafat Barat merupakan semacam catatan kaki atas pemikiran Plato. Sedangkan Aristotle sendiri merupakan tutor pribadi Alexander Agung yang jangkauan pemikirannya meliputi metafisika, logika, etika, politik, kritik sastra, dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian bila kita menjelajahi Google dengan kata kunci Plato atau Aristotle, maka akan ada banyak halaman yang muncul dengan relevansi konten sebagaimana yang kita baca melalui dalam buku sejarah filsafat. Tidak hanya sampai pada pendataan digital semata, dua tokoh ini juga merajai fiksi dan film.[1]
Lalu bagaimana dengan Horace? Halaman yang muncul dalam telusur Google mengantarkan pada situs Wikipedia dan situs-situs yang menyediakan karya puisi. Sejauh penelusuran di Google, saya tidak menemukan film atau fiksi yang secara khusus diatributkan untuk Quintus Horatius Flantus. Karakternya hanya hadir sebagai tokoh pelengkap cerita mengenai Augustus, penguasa Kekaisaran Romawi saat Horace hidup. Horace sendiri dikenal sebagai penyair liris Romawi, dengan karya penting Ars Poetica yang menekankan bahwa puisi adalah keprigelan penyair dan ia harus bisa menjadi contoh dan menawarkan kepuasan (to teach and delight). Bila memang Horace “hanya” dikenal sebagai penyair, mengapa Habib bersimpati padanya? Rasa simpati Habib pasti memiliki alasan. Ia merujuk pada Hegel, kemudian Marx dan Engels yang juga memberikan empati pada Horace. Seperti apa keistimewaan Horace? Apa kontribusinya pada kritik sastra? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari penyair yang kata Habib termasuk kaum kalah pengambil jalan tengah pada jamannya? Pertama-tama mungkin kita bisa berangkat menyelami kehidupan Horace pada era Augustus.
Era Kaisar Augustus: Tidak Seheroik yang Kita Kira
Horace (65 – 8 SM), anak seorang budak bebas, hidup saat Romawi berpindah haluan politik dari Republik ke Oligarki. Ia bersimpati pada kaum Republik, menjadi tentara untuk Marcus Iunius Brutus dan Gaius Cassius Longinus yang membunuh Julius Caesar. Brutus dan Cassius takut Romawi akan kembali menjumpai diktator semacam Julius Caesar sehingga meletuslah Pertempuran Philipp pada 42 SM. Kaum Republik berhadapan dengan Octavian Augustus dan Mark Anthony, namun akhirnya kalah di medan perang. Octavian Augustus kemudian diangkat menjadi Kaisar dan dikenal sebagai pendiri kekaisaran Romawi. Sejarah mencatat bahwa Augustus mampu mengakhiri perang saudara berkepanjangan dan menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kemegahan yang dikenal dengan sebutan Pax Romana.
Nasib Horace tampaknya cukup beruntung. Sekembalinya dari medan perang, Vergil mengenalkannya pada Gaius Maecena, sahabat sekaligus penasehat politik Augustus. Entah negosiasi yang terjadi seperti apa, akhirnya Gaius Macenas menjadi art patron (pelindung) Horace. Loyalitas Horace patut dipertanyakan. Mulanya ia mendukung kaum Republik tapi pada akhirnya mengabdi pada Augustus. Ia bisa mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak, hingga ia bisa menciptakan karya Ars Poetica yang secara teknis merupakan kritik sastra dan karya retoris namun dalam bentuk puisi. Pengalaman inilah, ingin tapi tidak ingin, yang membuat Horace sepanjang hidupnya terasa menduakan Augustus. Pernah ia diminta membuat puisi untuk Augustus. Alih-alih menunjukkan nilai-nilai Kekaisaran Romawi, ia malah menunjukkan subjektifitasnya sendiri: hidup sederhana, pikiran yang bebas dari rasa cemburu, dan kesetiaan pada dewi seni.[2]
Why do we aim so high, when time must foil our
Brave archery? Why hanker after countries
Heated by foreign suns? What exile ever
Fled his own mind? (Odes, II.16)
Bila dirunut lagi, sikap Horace yang mendua ada sebabnya. Kekaisaran Romawi memang memberikan ruang untuk kesusastraan, terutama bagi karya-karya yang menunjukkan nilai Romawi. Cuplikan Ode di atas merupakan gambaran posisi Horace yang berseberangan dengan kekaisaran Romawi.
Perkembangan ekonomi Romawi hanya terpusat pada produksi budak, dengan cara penjelajahan (penjajahan) dan jual-beli budak. Selebihnya, tidak ada perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi dari dalam kerajaan. Memang versi yang dipaparkan Habib tentang pemerintahan Augustus berbeda dari versi sejarah yang selama ini kita dengar. Habib sendiri merujuk pada Marx yang mengatakan bahwa pemerintahan Romawi kala itu merupakan pemerintahan yang paling buruk dimana yang terjadi adalah pemiskinan universal. Sedangkan teks Horace lebih condong untuk mempertanyakan peradaban Romawi.
Lalu bagaimana dengan perkembangan intelektual pada masa kekasisaran Romawi? Menurut Habib, membicarakan karya Horace tidak bisa lepas dari karya Vergil dan Ovid. Pemerintahan Augustus sendiri memiliki tiga pemikiran yang berkembang. Pertama adalah Stoisisme yang tercermin dari karya Aeneid dari Vergil (70 – 19 SM). Karya ini menunjukkan nilai-nilai Stoik berupa kealiman, kewajiban, disiplin diri dan mengorbankan kepentingan individu untuk kemaslahatan umat. Aeneid adalah tipe karya yang “ideal” bagi Augustus karena ia mampu menunjukkan sisi pemuliaan terhadap kekaisaran Romawi. Selain Vergil, kita juga harus ingat Ovid (43 SM – 17 M) dengan karyanya Ars Amoris yang merupakan antitesa dari Aeneid. Augustus menyensor Ars Amoris karena karya ini menujukkan nilai Sinisme dan Skeptisisme. Sedangkan karya Horace berada di antara dua penyair tersebut, condong ke pemikiran Epikureanisme, menekankan untuk sinis pada dewa-dewi dan tidak menganjurkan untuk terlibat secara sosial dan politis (dengan sistem).[3]
Horace juga Ikut Perdebatan Sastra
Meskipun ketiga penyair tersebut memiliki pandangan yang berbeda, mereka ternyata sama-sama mengafirmasi konsep imitasi sambil mencari konteksnya sendiri.[4] Aeneid karya Vergil misalnya. Ia memakai perlengkapan dan strategi seperti pada karya-karya epik Homer sembari menambahkan tema baru tentang takdir historis dan kewajiban individu. Selain itu, para pemikir Augustan juga mewarisi perdebatan para pemikir Alexandrian mengenai yang jenius (igenium) dan teknis. Horace juga ikut nimbrung dalam perdebatan tersebut. Pertama-tama mengenai ‘seni untuk seni’ dan ‘seni untuk masyarakat’. Horace mempertanyakan apakah sebuah karya semata untuk memberikan kenikmatan; ataukah kenikmatan tersebut bisa berguna untuk fungsi sosial, moral, dan pendidikan?
Horace akhirnya menawarkan jalan tengah dalam karya puisinya. Mengutip Habib, prinsip yang digunakan oleh Horace sendiri berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan teori: walaupun saat membicarakan teknik, ia lebih condong ke teori teknik dari Plato. Adapun tawaran Horace meliputi: (1) relasi penulis dengan karya, pengetahuannya tentang tradisi, dan kemampuannya sendiri; (2) karakteristik Ars Poetica sebagai struktur verbal meliputi kesatuan (unity), kesopanan/kepantasan (propriety), dan penyusunan (arrangement); (3) fungsi moral dan sosial sebuah karya, seperti mengembangkan kebijaksanaan, memberikan contoh moral melalui karakter, mengembangkan nilai sipil dan sensibilitas, sekaligus menyediakan kenikmatan untuk pembaca: (4) kontribusi pembaca (audience) pada komposisi karya, baik sebagai seni maupun komoditas; (5) kesadaran akan sejarah sastra dan perubahan bahasa dan genre.
Pertama-tama, saya mencatat bahwa Horace memiliki kesadaran pada publik sebagai audience. Bagi Horace, respon pembaca merupakan bagian dari penciptaan puisi sehingga seorang penyair harus paham mengenai perubahan suasana hati dan pergantian selera dari zaman ke zaman. Poin artistik sebuah karya berada di antara penyair dan audiens sehingga tak heran bila Horace menekankan bahwa estetika sebuah karya merupakan kombinasi praktis antara dua elemen tersebut. Sekali sebuah karya dipublikasikan maka kata-kata yang digunakan akan menjadi properti publik. Selain itu, Horace juga menyarankan bahwa untuk berkarya sebisa mungkin mengambil unsur-unsur yang dimengerti oleh publik sehingga pembaca nantinya bisa merealisasikan dan memahami karya.
Kedua, patut dicatat mengenai ambivalensi Horace mengenai sastra. Mulanya ia pernah berkata bahwa audiens merupakan publik yang bisa dihitung, tidak terlalu banyak, kebiasaannya murni, dan sikapnya sederhana. [5] Perkembangan Kekaisaran Romawi dengan banyak kota “jajahan” ternyata mempengaruhi cara pandang Horace mengenai publik. Semakin banyaknya populasi dan ragam penduduk Romawi membuat pengkaryaan “diberi kebebasan” terutama dalam pembuatan meter dan musik sehingga publik menjadi “tasteless”. Oleh sebab itu, Horace mengajukan pertanyaan sekali lagi, “karya sastra yang baik untuk era ini seperti apa?”. Jawaban Horace, yang condong menolak konsepsi ‘seni untuk seni’, akhirnya merujuk pada penggunaan karakterisasi dalam karya. Pandangan Horace ini tentu bertolak belakang dengan pandangan Aristotle yang menekankan pada pengembangan alur cerita. Namun, Horace tidak serta merta menyepakati tawaran Plato bahwasanya yang terpenting adalah visi moral dan menganggap bahwa puisi sebagai imitasi semata. Horace memang menyepakati pentingnya visi moral, tetapi ia juga menambahkan bahwa penyair yang baik adalah penyair yang pengetahuannya empiris dan detail. Imitasi bagi Horace adalah mampu menuangkan apa yang terlihat dalam keseharian penyair ke dalam sebuah karya.
Ketiga, berkaitan dengan pandangan estetika. Bagi Horace, estetika dipandang sebagai sesuatu yang praktis. Untuk bisa sukses secara finansial, karena bagi Horace yang utama adalah kenyang terlebih dahulu sebelum berkarya, maka penyair harus bisa menunjukkan fungsi estetis yang dipadukan dengan fungsi moral. Fungsi estetis berkaitan dengan konsep bentuk (form) yang ditawarkan oleh Horace dalam Ars Poetica. Selain itu, sebuah karya sebaiknya tidak hanya mampu menarik pembaca, tetapi juga dapat memberikan saran moral.
Visi Horace tentang Sastra
Horace memang dikenal hanya sebagai penyair otobiografis. Dalam bagian Horace ini, Habib ternyata berjalan jauh menyusuri sisi Horace yang jarang diungkapkan oleh buku sejarah. Habib memang terkesan berhati-hati dalam merangkai kata untuk Horace, terkadang menunjukkan simpati namun sering pula ia meraba mengenai warisan pemikiran Horace untuk kritik sastra. Berkali-kali Habib menekankan bahwa Horace termasuk tokoh jalan tengah dan mempertanyakan bagian pemikiran Horace yang orisinal dan berbeda dari zamannya. Pada bagian akhir Habib menggarisbawahi bahwa orisinalitas Horace terletak pada level form semata. Teks Horace dibaca sebagai contoh standar dari prinsip penyusunan (decorum), sebuah hubungan antara bentuk dan konten, ekspresi dan pikiran, style dan subject matter, diksi dan karakter. Horace selanjutnya menyatakan bahwa bentuk (form) ada dalam bahasa itu sendiri; bahwa konten sebenarnya tidak bisa berada di luar bentuk. [6]
Selebihnya Habib juga memposisikan Horace, mencari perbedaannya dengan Aristotle, Vergil, dan Longinus. Pertama, Habib mencatat adanya visi Horace mengenai ketidakharmonisan poetik dan politis. Kedua, penekanan pada kreasi individu, untuk bisa menjauhkan diri dari komitmen estetis dan politis. Pandangan Horace selalu merujuk pada motif praktis dalam pembuatan karya dan sebisa mungkin menghindari dampak metafisik, politis, dan keyakinan. Ia fokus pada kesegeraan mencipta karya, menganggap bahwa puisi sebagai bentuk keprigelan penyair. Penekanan Horace tersebut sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah kekaisaran Romawi. Betapa pun Augustus berdalih mengembangkan kesusastraan, namun pada akhirnya yang diterima adalah karya yang memuja Romawi. Horace sebagai seorang seniman, yang fatalnya harus berlindung di bawah patronnya sembari mengutuk Romawi setiap hari, tentu harus bernegosiasi dengan kehidupan macam itu. Satu-satunya jalan adalah menekankan pada subjektifitas individu.
You who write, choose a subject that’s matched by
Your powers, consider deeply what your shoulders
Can and cannot bear. Whoever chooses rightly
Eloquence, and clear construction, won’t fail him
(Ars Poetica, 38 – 41)
Penggalan puisi di atas tampaknya bisa menjadi pesan penutup sekaligus pengingat akan kehidupan Horace. Meskipun Horace menunjukkan dirinya sebagai orang bermuka dua di hadapan Augustus, tetapi ia tidak berhenti untuk mengeksplorasi kemampuannya untuk berkarya. Mengutip perkataan Engels, “Bayangkan lelaki jujur ini yang mencoba untuk melawan tirani Augustus. Meskipun ia selalu mendua, tetapi ia tetap dicintai.”[7]
[1] Beberapa karya fiksi yang memulai kisahnya dengan mengangkat dua tokoh legendaris ini misalnya, Dunia Sophie karya Jostein Gaarder (Penerbit Mizan, 1996); The Name of the Roses karya Umberto Eco (Bentang Pustaka, 2008) yang memberikan petunjuk mengenai tulisan Aristotle tentang komedi. Untuk manga (komik Jepang) meliputi: Iliad karya Uoto Osamu and Toshusai Garaku yang terinspirasi dari kisah Atlantisnya Plato dan Historie karya Hitoshi Iwaaki tentang Eumenes sekretaris Alexander Agung yang bertemu dengan Aristotle. Mereka juga hadir dalam seri dokumenter seperti Plato’s Republic (1996) dan Aristotle’s Lagon (Harry Killas, 2010). Monty Python, grup komedi asal Inggris, juga pernah membuat tribut untuk filsuf Yunani dan Jerman dalam The Philosophers’ Football Match dengan menghadirkan tokoh seperti Plato, Aristotle, Epikurean, Hegel, dan Kant dalam pertandingan fiktif di Olympiastadion.
[2] Habib, M. A. R. 2005. A History of Literary Criticism: from Plato to Present. (UK: Blackwell Publishing), hlm. 113.
[3] Ibid, hlm. 116.
[4] Ibid, hlm. 107.
[5] Ibid, 108
[6] Ibid, hlm. 108.
[7] Ibid, hlm. 117.


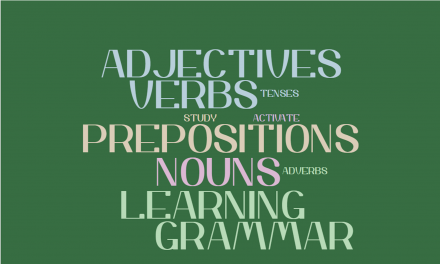



Komentar Terbaru