Sekilas Neoklasik[i]
Istilah neoklasik mengacu pada tendensi sastra dan seni secara umum dari awal abad ke-17 hingga sekitar tahun 1750. Ciri utama neoklasik adalah kembali ke model, gaya, dan nilai sastra klasik – yang sudah disajikan oleh para pengarang Yunani dan Romawi. Di titik ini, neoklasik bisa disebut sebagai pewaris Renaisans. Namun, para penulis neoklasik menolak kecenderungan Renaisans yang dianggap berlebihan dalam gaya dan ornamentasi, juga dalam merumitkan penggunaan bahasa. Mereka juga menolak gaya Gothik dan Barok.
Renaisans sering menekankan kemampuan individu meskipun di saat bersamaan menyerukan adopsi kanon klasik, sedangkan neoklasik lebih menegaskan pentingnya nilai objektivitas, impersonalitas, rasionalitas, decorum[ii], keseimbangan, harmoni, proporsi, dan moderasi. Terkait dengan itu, para penulis neoklasik cenderung menyoroti keterbatasan manusia—berkebalikan dengan kaum humanis dan Romantik yang mengamini ketidakterbatasan potensi manusia.
Tentang genre, Renaisans mendorong tumbuhnya genre baru dan campuran, sedangkan neoklasik cenderung menekankan pemisahan puisi dan prosa, kemurnian genre, dan hierarki genre (meski umumnya menempatkan epik di atas tragedi, tidak seperti Aristoteles).
Dua konsep utama dari teori dan praktik sastra neoklasik adalah imitasi dan alam. Gagasan imitasi – atas dunia eksternal termasuk tindakan manusia – merupakan peneguhan dari objektivitas dan impersonalitas, sebagai kebalikan dari kecenderungan individualisme dan subjektivitas ala Renaisans. Namun, yang juga termaktub dalam gagasan imitasi neoklasik adalah peniruan atas model-model klasik. Para penulis neoklasik umumnya memandang bahwa para penulis klasik seperti Homer dan Vergil sudah “menemukan” dan mengekspresikan hukum fundamental alam. Karenanya, dunia eksternal dapat diekspresikan dengan baik jika penulis modern meniru penulis klasik. Penemuan tentu diperbolehkan, tetapi hanya modifikasi, bukan penyimpangan, dari model klasik.
Alam, konsep utama lain dari neoklasik, punya makna yang luas. Pertama, alam mengacu pada tatanan semesta yang harmonis dan hierarkis, termasuk hierarki sosial dan politik yang ada di dunia—bahwa segala sesuatu dikodratkan punya tempatnya masing-masing yang sesuai. Konsep ini juga bermakna sifat manusia (human nature) – yang pokok, tak lekang waktu, dan universal dalam pengalaman manusia. Karenanya, nature punya makna moral yang dalam – mencakup model tindakan yang diizinkan dan mengeksklusi tindakan yang “annatural” (istilah yang sering dipakai Shakespeare untuk menggambarkan perilaku licik dan kejam dari tokoh dramanya, seperti Lady Macbeth).
Konsep lain dari neoklasik yang juga penting adalah rasio/ nalar. Meski konsep rasio para penulis neoklasik dipengaruhi oleh Newton – bahwa semesta merupakan mesin besar yang memiliki hukum yang tetap – mereka cenderung menggunakan konsep ‘rasio’ para filsuf klasik, yaitu kemampuan manusia untuk mengakses kebenaran umum dan kesadaran akan keterbatasannya. Rasio yang banyak dipakai adalah rasio Aristotelian dan kadang-kadang Horatian, yakni kepatuhan pada kemungkinan dan hal-hal yang tampak benar atau nyata (verisimilitude), tiga kesatuan (aksi, waktu, tempat) dan prinsip decorum.
Perlu diingat bahwa pada abad ke-17 kritik sastra mulai menjadi disiplin profesional dan terspesialisasi, dan sastra mulai diidentifikasi sebagai domain yang otonom. Selain itu, pasar sastra juga meluas, karya dicipta untuk aristokrat dan juga borjuis. Karenanya, dibutuhkan semacam panduan dan standarisasi mengenai selera yang baik. Standarisasi ini juga mencakup penggunaan bahasa dan makna kata. Di Prancis, Academie Francaise didirikan pada tahun 1635 untuk tujuan itu. Di Inggris, pada tahun 1755 Samuel Johnson menerbitkan A Dictionary of the English Language.
Pierre Corneille (1606)
Pierre Corneille adalah pengacara gagal yang kemudian menjadi seorang dramawan. Ia dikenal sebagai pembela nilai-nilai neoklasik dan sangat peduli dengan upaya untuk mengadaptasi resep-resep klasik demi kebutuhan modern. Karyanya, Three Discourses on Dramatic Poetry (1660), merupakan usaha untuk membela diri dari serangan kritikus yang menganggap bahwa karya-karyanya melanggar kesatuan klasik (aksi, waktu, dan tempat) serta resep kemungkinan dan keniscayaan Aristoteles. Dengan demikian, ia dituduh menggerogoti nilai didaktik drama.
Mari kita lihat sekilas cara Corneille membela diri dari serangan-serangan itu dan mencoba mengkontekskan resep klasik untuk kebutuhan zamannya.
Corneille mengamini pernyataan Aristoteles bahwa sebuah sebuah aksi yang lengkap harus memiliki awal, tengah, dan akhir. Namun, ia beranggapan bahwa sebuah drama tidak mesti berisi satu aksi saja. Bagian awal, tengah, dan akhir merupakan aksi yang berbeda yang akan menemukan kesimpulannya dalam satu aksi pokok (principal action). Dan masing-masing bagian itu dapat memiliki aksi sendiri. Dengan kata lain, Corneille setuju bahwa harus ada satu aksi lengkap, tetapi sebuah aksi yang lengkap hanya dapat dicapai dengan beberapa aksi lainnya. Aksi-aksi lainnya ini diperlukan, salah satunya, untuk memberikan suspense pada penonton. Di samping itu, menyetujui pernyataan Aristoteles bahwa semua peristiwa harus terjalin dalam koridor keniscayaan dan kemungkinan, Corneille menambahkan bahwa semua itu harus bersumber dari protasis (pengantar peristiwa di babak pertama).
Mengenai kesatuan waktu, Corneille membahas resep klasik Aristoteles bahwa aksi dalam tragedi harus berada dalam rentang waktu satu revolusi matahari. Para kritikus dan dramawan menafsirkan ‘satu revolusi matahari’ sebagai dua belas jam atau dua puluh empat jam. Corneille merasa bahwa resep itu harus ditafsirkan secara bebas. Rentang waktu aksi bisa, misalnya, hingga tiga puluh jam tergantung kebutuhan subjek yang diangkat. Kepatuhan mutlak pada batasan waktu 24 jam akan membuat banyak cerita klasik tidak mungkin dipanggungkan karena sebagian aksi melibatkan perjalanan tentara dan perang.
Bagi Corneille, bukan otoritas Aristoteles yang perlu dijadikan panduan untuk menyetel rentang waktu aksi, melainkan “akal sehat”. Puisi dramatik (naskah drama) merupakan imitasi atau gambaran mengenai tindakan manusia dan semakin dekat suatu penggambaran dengan kenyataan, semakin baiklah sebuah puisi. Atas dasar itu Corneille merekomendasikan untuk mempersingkat waktu aksi, untuk membuatnya lebih menyerupai kenyataan dan mendekati kesempurnaan.
Dari pendapat di atas, kita bisa menangkap perbedaan ‘realisme’ Aristoteles dan Corneille sebagai kriteria estetika. Realisme Aristoteles adalah realisme yang meniru dan menampilkan yang universal, kebenaran umum dari sebuah situasi; sebaliknya, realisme yang ditegakkan Corneille menekankan verisimilitude, penghadiran realitas dalam “dimensinya yang proporsional”. Dan, serupa dengan kesatuan aksi, dalam kesatuan waktu Corneille juga menekankan pentingnya audiens. Persoalan durasi waktu, menurut Corneille, semestinya dibiarkan menjadi imajinasi penonton.
Terakhir, tentang kesatuan tempat, Corneille mencatat bahwa tidak ada resep pasti dari Aristoteles dan Horace. Aturan mengenai tempat terbangun sebagai konsekuensi dari kesatuan satu hari, yang berarti bahwa tempat harus dapat dijangkau pulang-pergi oleh seseorang dalam waktu dua puluh empat jam. Tafsiran ini sedikit terlalu bebas, kata Corneille. Dengan tafsiran itu, dua sisi panggung bisa dipakai untuk merepresentasikan dua kota. Banyak situasi realistis yang tidak bisa dihadirkan dalam satu ruang.
Di satu sisi, Corneille ingin aturan yang lebih ketat, tetapi di sisi lain, aturan yang ketat akan menghambat dramawan menghadirkan kemungkinan aksi. Karena itu, Corneille mengambil kompromi. Misalnya, kita bisa menganggap bahwa seluruh kota sebagai sebuah kesatuan tempat, dengan syarat bahwa (1) pergantian adegan dilakukan antar, dan bukan dalam suatu, babak; dan (2) tempat-tempat yang berbeda tidak memerlukan perubahan setting panggung. Selain itu, mengadopsi istilah legal fiction[iii] dalam hukum, Corneille merasa bahwa dalam drama, kita juga bisa punya theatrical fiction. Misalnya, jika sebuah aksi drama dilakukan di sebuah rumah susun dan masing-masing rumah dimiliki oleh tokoh yang berbeda, kita bisa membangun sebuah ‘rumah’ yang berdampingan dengan rumah-rumah yang ada, tempat di mana setiap tokoh dapat berbicara bebas tanpa didengar oleh tokoh-tokoh lain.
Dalam penutup Three Discourses, Corneille menyatakan bahwa praktik dan pengalaman memainkan peran penting dalam negosiasi dengan aturan-aturan klasik. Kritikus bisa saja secara ketat menerapkan aturan-aturan klasik, tetapi jika mereka memproduksi teater, mereka akan bertemu dengan batasan-batasannya yang dapat membuat apa yang indah hilang dari panggung. Selain itu, penonton modern, yang memiliki selera yang berbeda dengan penonton klasik, juga harus diperhatikan. Tujuan utama Corneille adalah untuk “membuat aturan-aturan klasik setuju dengan kesenangan modern”.
Nicolas Boileau-Despreaux (1636-1711)
Boileau adalah penyair, satiris, dan kritikus Prancis yang memiliki pengaruh besar bukan hanya di kalangan sastra Prancis pada masanya, tetapi juga terhadap penyair dan kritikus Jerman dan Inggris. Karya kritik sastranya yang ditulis dalam bentuk puisi L’Art Poetique (The Art of Poetry), terbit kali pertama tahun 1674, merupakan pernyataan formal mengenai prinsip-prinsip klasisisme Prancis, dan mungkin merupakan gambaran prinsip neoklasik di mana pun.
Art of Poetry menunjukkan kecenderungan intelektual dan perubahan politik yang berlangsung di Eropa pada abad ke-17. Dalam karya itu, terlihat penolakan terhadap sistem feudal, cara berpikir khas neoklasik yang mengabaikan Abad Pertengahan dan berupaya untuk mengembalikan prinsip-prinsip klasik mengenai alam dan rasio, dan pandangan klasik mengenai manusia sebagai makhluk sosial.
Seperti dijabarkan di awal tulisan ini, rasio atau nalar yang dipakai oleh para pemikir neoklasik, termasuk Boileau, adalah nalar klasik, yaitu kemampuan manusia dalam merasakan apa yang secara universal benar. Nalar Boileau bukanlah nalar borjuis yang menolak semua otoritas dan bertumpu pada penemuan indrawi individu. Tidak mengherankan bila Boileau dalam tulisannya menjunjung tinggi otoritas Prancis Louis XIV sebagai raja besar yang menghalau pemberontakan dan menghadirkan ketertiban di Eropa.
The Art of Poetry ditulis dalam bentuk puisi, mengafirmasi dirinya sebagai bagian dari tradisi Horatian. Dan memang, di Canto I, nasihat Boileau yang diperuntukkan bagi para penyair sangat kental rasa Horace-nya. Ia menekankan agar penyair memahami kekuatan dan kedalamannya sendiri, terus-menerus memoles karyanya, dan tidak terjebak pada puji-pujian. Ia memperingatkan penyair agar menghindari detail yang berlebihan dan tidak perlu, dan meragamkan wacananya demi menyenangkan pembaca. Seperti Horace, ia menekankan fungsi sastra sebagai penyedia instruksi sekaligus kesenangan. Sampai di titik ini, tampak tidak ada yang orisinal. Baru setelah teks Boileau bergerak melampaui Horace dengan menghadirkan perkembangan retorika dan pemikiran di masanya dan di masa Horace, serta pengangkatan rasio sebagai pusat seluruh gagasan klasik, kita menemukan upaya pembangunan kritik sastra ala Boileau.
Memang, prinsip rasio merupakan inti dari pemikiran Boileau. “Whate’er you write of pleasant or sublime,” kata Boileau, “Always let sense accompany your rime.” Perimaan tidak boleh mendikte arah dan alur puisi; ia harus tunduk pada rasio karena rasio-lah yang melindungi penyair dari false glittering poetry dan extravagant and senseless objects. Di sini, rasio berfungsi sebagai kontrol agar penyair mampu menahan diri untuk tidak secara berlebihan menghadirkan sesuatu—moderasi khas klasik. Para penulis klasik, seperti Homer dan Vergil, dianggap Boileau patut dicontoh karena kemampuan mereka untuk tidak terjebak pada ekstrem, pada yang berlebih-lebihan.
Dalam pandangan Boileau, rasio juga berfungsi untuk menghindarkan puisi dari puritanisme agama. Boileau memahami perbedaan pandangan antara pagan/klasik dengan ajaran Kristiani dan menganggap bahwa ajaran Kristiani tidak cocok untuk dijadikan subjek puisi; di sisi lain, menghilangkan ornamen klasik akan memiskinkan puisi. Karena itu, ia membuat pemisahan yang tegas: Tuhan dalam ajaran Kristiani tidak bisa dicampur dengan dewa-dewa Pagan. Agar Tuhan Kristiani tetap murni dan benar, penggambaran mengenainya harus dibatasi pada teologi dan ajaran-ajaran; ia tidak boleh masuk domain puisi. Pandangan ini di masa selanjutnya dianggap mengabaikan karya-karya Abad Pertengahan, seperti yang ditulis Dante, yang berupaya menggantikan mitologi klasik dengan mitologi Kristiani atau paling tidak mencoba memodifikasinya.
Boileau berseru kepada penyair agar mereka mempelajari alam dengan sungguh-sungguh. Penyair harus mengetahui sifat dan rahasia hati manusia. Ia harus mengamati dan mampu melukiskan semua jenis manusia, baik muda maupun tua. Kemampuan untuk menghasilkan decorum ini—bahwa yang muda harus bicara seperti orang muda, orang tua harus bicara seperti orang tua, orang dari daerah tertentu harus bicara layaknya seperti orang dari daerah itu—bagi Bolieau, merupakan hasil dari praktik nalar.
Terakhir, rasio ditempatkan Boileau dalam isu mengenai hubungan antara proses kreatif dengan aturan, khususnya terkait kemampuan untuk membangkitkan perasaan dan emosi pembaca. Senada dengan Sidney, Boileau menganggap bahwa sebelum mengajari, puisi pertama-tama harus memberi kesenangan. Untuk mampu menghasilkan puisi yang memberi kesenangan, penyair justru tidak boleh terlalu patuh pada aturan. Ia harus tahu kapan mesti mengikuti aturan. Dengan kata lain, rasio di sini disamakan bukan dengan pengamatan penyair tentang aturan, tetapi dengan pengetahuan mengenai kapan seorang penyair harus mengikuti aturan.
Meski menekankan pentingnya fungsi sastra untuk menyenangkan pembaca, Boileau memperingkatkan penyair untuk tidak terjebak pada hasrat keberhasilan sementara, untuk tidak menurunkan derajat puisinya menjadi sekedar barang dagangan, untuk tidak tergoda dengan puji-pujian patron. Penyair mesti mengejar “ketenaran abadi”!
_____________
[i] Tulisan ini disarikan dan mengikuti alur tulisan MAR Habib dalam A History of Literary Criticism, hal. 273-284.
[ii] Standar kepantasan yang dengannya gaya, karakter, bentuk, dan tindakan dalam karya sastra dianggap saling sesuai satu sama lain dalam sebuah model yang hierarkis. Decorum memberi peringkat genre ke dalam ‘tinggi’, ‘tengah’, dan ‘rendah’ dan menuntut gaya, karakter, dan tindakannya sesuai dengan level-level itu. Misalnya, epik atau tragedi harus ditulis dalam gaya ‘tinggi’ tentang tokoh-tokoh yang melakukan tindakan besar. (Lih. penjelasan lebih lengkapnya di Oxford Dictionary of Literary Terms). Dalam rangkaian tulisan di mediasastra.net sejauh ini, konsep decorum dapat ditemukan dalam tulisan mengenai Horace dan de Vinsauf.
[iii] Sebuah fakta yang diasumsikan atau diciptakan oleh pengadilan/juri, yang digunakan untuk membantu mencapai sebuah keputusan atau untuk mengajukan aturan hukum. Dengan kata lain, legal fiction mengasumsikan sesuatu yang jelas salah sebagai benar. Di Romawi, misalnya, sebuah keluarga memerlukan anak laki-laki sebagai pewaris. Ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga diatasi dengan sebuah legal fiction berupa adopsi. Dengan adopsi, seorang anak laki-laki diberi identitas baru dan sebuah keluarga dianggap punya anak laki-laki sebagai pewaris.




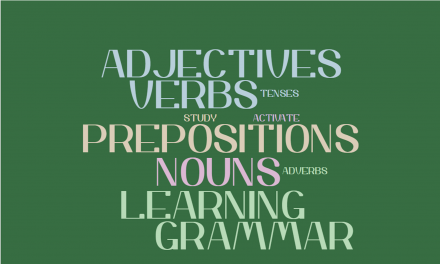

Komentar Terbaru