Sudah cukup lama di dalam tubuh tim Mediasastra.com—yang sebagian besar bertitel S.S.—muncul banyak grundelan[i] tentang pendidikan sastra yang telah didapat di pendidikan formal. Di setiap ujung grundelan, semuanya sepakat bahwa pendidikan (kritik) sastra yang pernah ditempuh jauh dari memuaskan (jangankan memuaskan, ‘bikin geli’ saja belum). Karenanya, terasa berat sekali ketika kami hendak menulis sejarah kritik sastra: kami harus sangat sibuk seperti memulai dari awal lagi karena kurangnya pemetaan di kepala. Kami pikir, seharusnya peta (sejarah) semacam itu merupakan pengetahuan umum dan mendasar dari seorang lulusan Fakultas sastra. Yang membuat semuanya makin menyesakkan adalah bahwa kini kami dihadapkan dengan pembicaraan tentang dan sekitar sastra yang sudah na’udubillahmindallik bentuknya. Teori-teori yang dipakai—mulai dari yang tanpa ‘pasca’ hingga yang ‘pasca’-nya pakai kuadrat—sangat beragam dan acak. Bahkan kini sedang hyped untuk menumpuk-numpuk teori dalam satu tulisan saja! Kan amsyong jadinya jika kami masuk ke diskusi-diskusi yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan semacam itu tanpa memiliki peta karena yang nulis esei-esei tadi aja belon tentu punya.
Akhirnya, di suatu senja pada pertengahan tahun 2014 lalu, setelah beberapa tahun kami nggrundel[ii] – dan belajar beberapa teori lagi entah hasil iseng maupun sekolah lagi – kami memutuskan untuk menata kepala kami kembali melalui sebuah kelas kritik sastra. Kami pun mulai mencari buku panduan yang tepat yang ternyata bukan pekerjaan mudah karena buku pengantar tentang sejarah dan teori sastra jumlahnya melebihi jumlah museum militer yang dibangun Soeharto. Gilanya, dapat dikatakan, setiap kampus di Barat yang memiliki jurusan sastra menerbitkan buku pengantarnya sendiri. Karenanya, demi mendapatkan panduan yang pas, kami pun berkelana ke perpustakaan dan situs-situs penyedia buku.
Dalam pencarian, kami bertemu dengan seorang Empu bernama M. A. Rafey Habib, seorang keturunan India besar di Inggris yang kini mengajar di Rutgers University-Camden, Amerika Serikat (dulunya merupakan Profesor Bahasa Inggris di Kingston University, London). Di tangannya terdapat sebuah kitab pengantar yang sepertinya sesuai dengan kebutuhan kelas kritik sastra kami, yakni A History of Literary Criticism: from Plato to Present (2005). Buku tersebut – dengan cukup mencolok – berbeda dengan beberapa buku pengantar lain yang telah kami telusuri sebelumnya. Buku Habib begitu kaya akan pandangan-pandangan baru dengan pemaparan latar sosial-politik pemikiran dan jalinan satu pemikir(an) dengan pendahulu maupun penerusnya. Di ujung pencarian, kami pun memutuskan untuk menggunakan buku ini sebagai buku panduan utama, menjadikan bab-bab di dalamnya sebagai acuan alur (dan jadwal) kelas kritik sastra dua mingguan. Pun demikian, kami tetap terbuka dengan sumber-sumber lain sejauh dibutuhkan. Tulisan singkat ini—yang akan diikuti tulisan-tulisan singkat setelahnya—adalah rangkuman, catatan, dan refleksi dari obrolan di setiap pertemuan. Kini saya akan membahas Plato, orang yang di beberapa buku pengantar selalu diposisikan sebagai pemikir pertama yang membicarakan sastra(wan).
Filsafat adalah panglima!
Jika dilihat dari rangkuman Habib atas estetika Platonis, dapat dikatakan bahwa Plato bukanlah penggemar berat kejantanan Achilles ketika menantang Agamemnon dengan menarik pasukannya ataupun lika-liku hubungan Oedipus-Jocasta. Di tulisan-tulisannya (dialog-dialognya) ada banyak sekali gugatan yang diajukan Plato terhadap sastra, seperti posisi sosial-politiknya, keabu-abuan ranahnya, dan kebenaran yang dikandungnya. Plato bahkan tidak hanya bermasalah dengan karya dan sastrawan di masanya dan masa-masa sebelumnya namun ia juga bermasalah dengan konsep karya sastra itu sendiri. Bagi Plato ada sesuatu yang an sich salah dengan sastra. Can you feel the irony? Maksud saya, orang yang didaku sebagai kritikus sastra pertama di dunia merupakan seseorang yang skeptis sekali terhadap keberadaan karya sastra dan kepopulerannya. Sebelum lebih jauh membahas kritik Plato, saya ingin terlebih dahulu menunjukkan pembedaan yang dilakukan Plato atas filsafat dan tradisi puitika.[iii]
Perbedaan pertama yang disuguhkan Plato terkait dengan basis pengetahuan keduanya. Menurut Plato, sebagaimana dirangkum oleh Habib, “the former (sastra-pen.) has its very basis in a divorce from reason, which is the realm of philoshopy”.[iv] ‘Reason’ (logos) sendiri – yang saya artikan sebagai akal sehat atau nalar – terkait dengan asal-muasal munculnya pemikiran filsafat dan metode berpikirnya. Sebagai contoh penggunaan ‘reason’ sebagai basis pemikiran fisafat, Plato memperkenalkan konsep ‘dialektika’ untuk mencari dan menilai kebenaran dalam sebuah subyek. Dalam ‘dialektika’, dua wacana yang berbeda tentang sebuah subyek dipertemukan dan ditandingkan melalui argumentasi yang berlandaskan akal sehat dan bukan emosi (pathos). Sedangkan sastra “in its very nature is steeped in emotional transport and lack of self-possesion”.[v] Artinya, tidak seperti filsafat yang segala usahanya dimaksudkan untuk menggapai kebenaran, karya sastra hanya bermaksud untuk memicu tanggapan emosional pembacanya. Melalui sastra, orang-orang digerakkan oleh dorongan emosi dan bukan pengetahuan akan kebenaran.
Pembedaan kedua terkait dengan kadar kebenaran dalam ajaran di dua ranah tersebut. Filsafat dapat mengajarkan kebenaran kepada orang-orang sedangkan sastra, melalui panggung-panggungnya, tidak. Alasannya, filsafat berurusan langsung dengan fenomena-fenomena yang ada; si filsuf datang dengan sebuah pemaknaan atas sebuah fenomena yang kemudian dibicarakan bersama di sebuah forum. Di sisi lain, sastra tidak membawakan fenomena-fenomena tadi secara langsung. Ia harus melewati panggung-panggung yang ada. Dengan kondisi semacam itu, para penonton teater sesungguhnya hanya disuguhi tiruan (interpretasi) dari karya para penyair melalui para pemain teater. Menggunakan logika tiruan ini, para anggota forum filsafat dapat dikatakan menerima tiruan tangan pertama (dari si filsuf yang memaknai sebuah fenomena) sedangkan para penonton teater hanya mendapatkan tiruan dari tiruan. Dengan begitu kadar kebenaran yang diterima melalui filsafat jauh lebih tinggi.
Pembedaan berikutnya terkait dengan visi yang dibawa dua tradisi tersebut. Di pemikiran Plato, tujuan filsafat adalah “…to stabilize that world, drawing all of its scattered elements into the form of order and unity under which alone they can be posited as absolute and transcendent…”.[vi] Mungkin akan lebih jelas jika dikatakan bahwa proyek filosofis Plato adalah untuk memayungi segala bentuk pemaknaan dalam sebuah kebenaran mutlak, yang mana kebenaran ini akan dijadikan pegangan untuk menjalankan dunia. Tradisi sastra, bagi Plato, berada di poros yang lain dan mengganggu. Alasannya, “…poetry offers a vision of ungovernable and irreducible multiplicity where the transcendence of any ideal is only sporadically and therefore incompletely achieved.”[vii] Tradisi sastra di sini dipandang cenderung menerima segala bentuk interpretasi atas dunia. Dengan begitu, tradisi ini tidak dapat dijadikan pegangan untuk mencapai dunia yang teratur dan terarah.
Nah, tiga pembedaan Plato ini, dengan standar-standarnya, lantas tidak hanya memisahkan ranah filsafat dan sastra namun juga menempatkan keduanya di posisi yang tidak sejajar – filsafat jelas lebih superior dibandingkan sastra. Di bagian berikutnya, saya akan menelusuri dasar ‘stratifikasi’ Plato ini sekaligus kritik Plato lebih jauh terhadap tradisi puitika.
Pengadilan sastra dari dalam gua dan negara
Jika dilihat dengan lebih seksama, klasifikasi Plato di atas dapat dibaca sebagai ‘serangan’ terhadap tradisi sastra. Di klasifikasi tersebut, sastra dianggap tak memiliki alur pemikiran yang jelas terkait dengan produksi pengetahuannya. Sastra juga dianggap tak mampu memberi kebenaran yang dibutuhkan masyarakat dan dianggap memiliki kecenderungan menjauhkan masyarakat dari persatuan (unity). Akan tetapi, jangan salah, Plato tidak berhenti sampai di situ saja. Ia sama sekali tak main-main dengan kritiknya terhadap puisi dan panggungnya. Kritiknya terhadap puisi dan panggungnya ini bukanlah ‘iklan’ yang cuma numpang lewat. Kritiknya tersebut adalah bagian penting dari pemikiran Plato secara umum. Karenanya, kritik terhadap kedua hal tadi hampir selalu muncul di pemikiran di bidang lain seperti pendidikan dan politik. Bahkan, lebih jauh, menurut Habib, kritik terhadap puisi ini terkadang menjadi hal yang menyusun buku-buku Plato seperti Ion.[viii] Jadi, mari kita mulai dalami kerangka berpikir dan kritik Plato lebih jauh satu per satu dimulai dari ranah politik.
Pada ranah politik, salah satu hal baru yang saya dapat ketika membaca Habib mengenai Plato terkait dengan superioritas filsafat atas tradisi sastra adalah pengangkatan filsafat ini bermuatan politik (politically-motivated). Penilaian tersebut datang dari kerangka berpikir Plato yang mencoba mencari fungsi tradisi sastra di masanya terutama panggung teater dalam sebuah negara (polis). Itu berarti, menurut Habib, jika kita ingin menilai kritik Plato atas tradisi sastra, kita juga harus mempertimbangkan konsep polis dan sistem politik idealnya sekaligus posisi politis karya sastra di masa Plato hidup. Pertanyaannya, kenapa Plato merasa perlu ‘menyerang’ karya sastra – dan tentu beserta panggungnya – dengan menempatkannya dalam konteks sebuah polis yang baik?
Yang pertama berhubungan dengan posisi penting panggung teater di masa itu yang jauh lebih ‘dianggap’ oleh masyarakat dibandingkan dengan filsafat. Di masa tersebut, panggung teater yang mengangkat naskah-naskah klasik bertindak mirip seperti media sosial, media massa, dan kuliah umum di masa kini. Karenanya, panggung sastra sangat kuat dalam membentuk (mengarahkan) opini publik. Padahal, seperti telah kita ketahui dari pembedaan sastra-filsafat di atas, menurut Plato, sastra tidak layak dijadikan acuan bagi masyarakat umum. Kedua, terciptanya negara yang kuat adalah hal yang yang sangat mendesak di masa Plato. Jika melihat perjalanan hidup Plato, ia lahir dan besar di masa Perang Peloponnesian (431 SM hingga 404 SM). Artinya, ia menjalani sepertiga hidupnya di dalam kondisi perang dan dalam kondisi perang sebuah negara harus solid agar dapat memenangkan perang. Itulah tampaknya yang sangat membekas dalam diri Plato sehingga ia menakar kegunaan panggung teater melalui sudut pandang keutuhan dan kekuatan sebuah negara.
Dengan latar belakang semacam itu, puisi dan panggungnya menjadi masalah bagi kekuatan sebuah polis. Puisi dan panggungnya dianggap dapat merongrong kekuatan sebuah polis karena keduanya terlalu mengedepankan keberagaman (lihat poin ketiga di bagian sebelumnya) dan meminggirkan visi bersama dalam diri rakyat Yunani. Padahal, menurut Plato, persatuan dalam sebuah polis adalah yang terpenting. Lebih lanjut, kali ini terkait dengan si pencipta karya (penyair), penyair dianggap tidak memiliki sebuah spesifikasi (tugas) yang jelas di dalam sebuah polis. Ia tampak mampu berbicara tentang apa saja dan mengerti semuanya seperti terlihat dalam karya-karyanya padahal hirarki dan pembagian kerja adalah hal yang mendasar di pandangan politik Plato selain unity. Karenanya, tak mengherankan jika seorang penyair harus ‘dibuang’.
Jika dikaitkan ke sistem politik, bagaimana sebenarnya konsep unity Plato ini? Konsep unity untuk Plato adalah konsep mendasar sebuah demokrasi. Akan tetapi, bukan itu saja yang penting. Unity harus diikuti dengan hirarki yang jelas. Jadi, dalam persatuan tersebut masing-masing lapisan masyarakat harus mengerti posisi dan fungsinya. Tradisi puitika, menurut Plato, membawa ide demokrasi yang gila kebebasan. Di bukunya Habib menulis, menurut Plato, “[l]ike democracy, poetry fosters genuine individuals…and resist the reduction of their social function, or indeed their natural potential, into one exclusive dimension. Also, like democracy, poetry nurtures all parts of the soul, refusing obeisance to the law of reason.”[ix] Walhasil, demokrasi yang dibawa tradisi puitika adalah demokrasi yang rakus akan kebebasan dengan titik berat pada individualisme dan kekacauan (ketidakteraturan); tidak seperti demokrasi dalam bayangan Plato yang mengedepankan persatuan dan hirarki. Jenis demokrasi yang dibawa tradisi puitika ini berbahaya, menurut Plato, karena ia justru membawa masyarakat ke tirani, yang membuat negara akan menanggapi kondisi kacau tersebut dengan kekerasan. Untuk menjauhkan dari peran negara yang semacam itu muncul, hirarki dalam demokrasi menjadi penting. Dengan sudut pandang seperti ini, demokrasi Plato sesungguhnya lebih condong ke sistem aristokrasi karena persatuan dalam sistem tersebut hanyalah
effectively a euphemism for a system of dominance, a rigid hierarchy whereby the “lower” (referable to the body, the appetites, or the majority of people in a state) is not merely subsumed under the “higher” but is divested by such subsumption of any independent claim to reality, meaning, or value.[x]
Ditambah dengan penunjukan philosopher-king[xi] sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah polis, semakin jelaslah bahwa demokrasi Plato ini lebih condong ke arah Aristokrasi.
Kembali ke ketakteraturan pada tradisi puitika. Plato merumuskan hal tersebut ketika memperhatikan cara para sastrawan menarasikan hubungan manusia-dewa yang tak mengindahkan adanya hirarki. Para dewa, di karya-karya Homer sebagai contoh yang digunakan Plato, tidak bertindak selayaknya dewa yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Mereka terlalu ‘manusia’, bahkan hanya menjadi perpanjangan tangan manusia, seperti misalnya dalam kasus balas dendam. Contoh nyatanya ada di The Illiad-nya Homer. Di awal karya tersebut diceritakan bahwa pasukan Agamemnon dan Achilles diserang wabah penyakit. Wabah tersebut ternyata adalah kutukan dari Apollo yang mengabulkan permintaan Chryses – pendeta kuil Apollo yang anaknya (Chryseis) diculik oleh Agamemnon. Perendahan posisi dewa yang seharusnya menjadi pemimpin inilah yang dimaksud oleh Plato. Dengan narasi-narasi semacam itu, para pembacanya tidak akan menghormati pemimpinnya karena tak ada keteraturan (bahasa TNI-nya tidak ada garis komando yang jelas) padahal sebuah polis harus teratur dengan garis komando jelas (siapa bekerja apa, ke arah mana dan menuruti [si]apa). Lebih jelasnya, Polis yang Plato bayangkan akan dipimpin oleh Philosopher-King yang – sebagai perlambang persatuan (raja) dan kebaikan bersama (filsuf) – akan memberi arah pada perjalanan polis ke depannya.
Dari paragraf-paragraf di atas, kita telah dipertemukan dengan konsep-konsep khas Plato seperti unity, hirarki dan Philosopher-King. Di bagian ini dua konsep tersebut dan konsep-konsep lainnya akan disambungkan dengan teori-teori filsafat Plato. Teori Plato yang sangat berpengaruh hingga kini dan wajib digunakan untuk memperkenalkan pemikiran Plato adalah Theory of Forms (Teori Bentuk). Jadi, kini saya akan membangun jembatan antara konsep-konsep di paragraf-paragraf sebelumnya dengan Teori Bentuk Platonis. PadaTheory of Forms-nya, yang ditemukan Habib di tulisan masa tengah Plato seperti Phadeo dan Republic, Plato menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada – yang dapat ditangkap indra manusia – di kehidupan sehari-hari hanyalah imitasi dari sebuah esensi yang berada di dunia ide.[xii] Sebagai sebuah imitasi, ia hanya bermakna ketika kita mampu melihat ide yang ada di baliknya karena, pada dasarnya, di dunia ide yang universal (berlaku untuk semua imitasi) dan tetap (makna di dunia ide tidak berubah-ubah layaknya imitasi yang terlihat) inilah makna sesungguhnya dari imitasi tadi berada.
Pandangan ini umumnya, seperti yang juga dilakukan oleh Habib, dijelaskan menggunakan allegory of the cave (allegori gua)[xiii] Plato yang ada di bagian pembuka buku ke tujuh The Republic. Di alegori tersebut, Plato mengajak pembacanya untuk membayangkan sekelompok orang yang ditahan di dalam gua sejak kecil dengan tangan dan kaki terikat ke tonggak-tonggak kayu. Dengan kondisi itu, para tahanan hanya dapat melihat ke satu arah (dinding gua). Di belakang mereka, sekelompok orang memegang benda-benda yang bayangannya dijatuhkan ke dinding tadi dengan bantuan sebuah unggunan api di belakang mereka. Kemudian, oleh Plato digambarkan bagaimana para tahanan tadi mulai beradu argumen mengenai benda-benda yang mereka lihat di dinding gua. Masing-masing merasa mengetahui benda-benda tersebut tanpa menyadari bahwa sesungguhnya benda-benda yang mereka lihat hanyalah bayangan saja.
Alegori gua digunakan Plato untuk menggambarkan kondisi manusia ketika berhadapan (memaknai) fenomena di sekitarnya: semua fenomena yang terlihat hanyalah bayangan dari sebuah ide. Di sini, sekali lagi, Plato lebih mengedepankan dunia ide – sebagai sumber segala makna – karena yang terlihat hanyalah imitasi. Inilah alasan Plato, oleh pemikir-pemikir setelahnya, digolongkan sebagai filsuf Idealis. Plato yakin bahwa esensi mendahului eksistensi (imitasi) dan, tidak hanya sampai di situ, makna (esensi) sebuah eksistensi tidak berada an sich di dalam eksistensi tadi.
Teori Bentuk ini jelas memiliki beberapa dampak pada definisi sastra yang mana terkait dengan pembedaan sastra-filsafat sebelumnya. Pertama, berhubungan dengan pembedaan sastra-filsafat poin kedua, karya sastra bagi Plato tidak membawa kebenaran yang hakiki. Kadar kebenaran yang dibawa patut diragukan. Alasannya, karya sastra hanyalah sebuah imitasi. Lebih tepatnya karya sastra hanyalah imitasi dari imitasi karena yang ada di dalamnya hanyalah tiruan dari kehidupan sehari-hari yang sebenarnya hanyalah tiruan juga. Menggunakan logika gua tadi, karya sastra setara dengan pembicaraan para tahanan yang diikat mengenai bayangan yang ada di dinding gua. Artinya, sastra sama sekali tak membicarakan barang asli yang terpapar api. Ia hanya sampai di titik bayangannya. Jika ditilik dari posisi seorang rhapsode seperti Ion dalam Ion dan para pemain teater lain, mereka tidak lain adalah orang-orang yang meniru sebuah tiruan dari sebuah tiruan. Dengan proses semacam itu Plato lantas merasa pantas untuk meragukan manfaat dari panggung-panggung teater bagi rakyat Yunani.
Selain kadar kebenaran yang meragukan karena level tiruan tadi, kali ini terkait dengan pembedaan sastra-filsafat poin pertama, kritik Plato juga menyasar dasar pencarian kebenaran yang ‘salah’ dari para penyair (sastrawan). Menurutnya, para sastrawan tadi hanya sibuk dengan imitasi (fenomena keseharian) saja dan melupakan esensi pemicunya. Seperti dalam penarasian ‘keadilan’, para penyair dianggapnya terlalu sibuk menggambarkan dalam bentuk balas dendam dan saling bunuh – yang lebih mengaduk emosi – daripada menunjukkan apa itu keadilan secara mendasar dengan bertanya ‘apakah membunuh seorang pembunuh adalah keadilan?’[xiv] Di sini, Plato menganggap emosi (pathos) menjadi dasar pengetahuan tradisi berpikir sastra. Padahal emosi, bagi Plato, adalah sisi terendah – jauh di bawah reason (logos) dalam intelektualitas seseorang.
Yang ketiga, terkait dengan konsep unity, Plato sebagaimana terlihat dalam Teori Bentuk-nya lebih menitikberatkan pada Yang Universal. Ingat, berdasarkan Alegori Gua, para tahanan (manusia) dianggap tak tahu apa-apa oleh Plato karena mereka tak pernah tahu ada api yang memancarkan cahayanya pada barang-barang dan menghasilkan bayangan di dinding. Itu berarti jika kita ingin mengetahui sebuah makna dari sebuah fenomena, kita harus mengetahui sumbernya karena hanya dari titik itulah fenomena tadi memiliki makna. Artinya, makna diberikan oleh sesuatu yang universal, seperti api, pada sesuatu yang partikular seperti barang-barang. Lebih jauh, hubungan ini adalah hubungan satu arah dari yang universal ke yang partikular. Itulah kenapa di bukunya Habib menyimpulkan bahwa, di benak Plato,
it is only the enabling ideal Form (such as beauty) of an object which can be studied “in itself.” The object itself cannot be so studied and is thereby reduced to purely referential status, pointing beyond itself to the Form of which it is merely the superfluously unique material realization.[xv]
Dengan begitu, berfokus pada imitasi-imitasi yang ada seperti pada karya sastra untuk mencari makna, sesungguhnya adalah usaha yang sia-sia.
Titik berat Plato pada Yang Universal dalam proses pencarian makna juga terlihat di konsep polis-nya – terutama cara melihat posisi-posisi subyek dalam sebuah polis. Pada konsep polis Plato, seorang pandai besi hanya akan berfungsi dengan baik jika ia bekerja demi negaranya dengan menyediakan pedang atau ujung tombak bagi para prajurit. Pandai besi di contoh ini memiliki posisi sebagai yang partikular dan negara sebagai yang universal. Karenanya, si pandai besi harus luruh dalam sebuah negara dengan menjadi, seperti kata Pink Floyd, ‘another brick in the wall’ agar keberadaannya bermanfaat. Di sini Plato tidak memandang bahwa spesialisasi si pandai besi ini (yang partikular) mungkin memiliki pengaruh pada berjalannya sebuah negara (yang universal). Plato tak berpikir, misalnya, seluruh pandai besi di Yunani hanya mampu membuat pedang. Dengan kondisi tersebut tentu strategi perang Yunani tak mungkin strategi perang jarak jauh. Jika para pandai besi hanya dapat membuat anak panah dan busurnya tentu lain ceritanya. Yunani tentu akan berusaha menjebak musuhnya dalam perang jarak jauh. Nah, konsep universalisme idealis Plato inilah yang akan sangat berpengaruh karena memantik banyak perdebatan yang bahkan dimulai sejak Aristoteles.
Setelah menelusuri pemikiran Plato secara lebih mendalam, bagian berikutnya akan saya dedikasikan pada warisan-warisan Plato di dunia sastra.
Kita, Sang Platonis yang Bangga!
Plato mungkin telah meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu dan hal-hal yang ia bicarakan di atas bisa jadi terasa asing bagi kita, namun bahasanya jelas masih melekat di ujung lidah kita. Sadar atau tidak sadar, klaim-klaim kita seringkali masih sangat platonis dan beberapa orang, termasuk beberapa pemikir, masih menganggapnya sebagai sesuatu yang progresif (relevan). Saking mengerikannya, klaim-klaim tersebut terkadang muncul dari mereka yang sama sekali belum pernah membaca dialog-dialog Plato atau dalam pengaruh 1 amplop daun surga. Artinya, klaim-klaim platonis tersebut telah menjadi bagian dari spontanitas kita dan, menurut saya, sekuat-kuatnya pengaruh adalah ketika mereka yang terpengaruh tak merasa sedang dalam pengaruh orang lain.
Apa saja kah warisan Plato yang masih mempengaruhi kita hingga saat ini? Yang pertama adalah klaim bahwa filsafat dan sastra memiliki ranah yang berbeda. Mungkin dalam pembedaan Plato tersebut sastra diletakkan di bawah filsafat akan tetapi, seberapapun rendahnya, sastra di titik tersebut tetap dianggap sebagai sebuah tradisi tersendiri dengan logika tersendiri. Ia pun dapat dikaji dengan beberapa sudut pandang seperti sosial dan politik sebagaimana dicontohkan sendiri oleh Plato. Agak ironis memang yang dilakukan Plato: meski bermaksud menurunkan derajat sastra, ia malah menjadikannya disiplin tersendiri. Bahkan ia meletakkan batu-batu pertama dalam hal tata cara menilai karya sastra.
Warisan kedua, berkaitan dengan tata cara di atas, adalah penempatan didaktisme sebagai obyek penelitian dan diskusi sastra. Selama mengkritik kegunaan sastra bagi masyarakat dan negara, Plato menempatkan sastra sebagai sebuah pengajaran meskipun kini kita tahu bahwa bukan pengajaran yang baik. Perdebatan tentang didaktisme (sastra sebagai pengajaran) ini di dunia sastra adalah perdebatan yang tak pernah habis dimakan waktu. Ia selalu mampu muncul bahkan melalui teori-teori (ideologi-ideologi) yang tampak saling tak berkaitan dan mungkin bertentangan. Sebagai contoh, kita ingat di Indonesia pertentangan antara Manikebuis dengan Lekra pernah sangat gencar dan kentara. Dua golongan yang sangat berbeda secara ideologis ini nyatanya saling setuju bahwa karya sastra dipenuhi dengan nilai. Para Manikebuis percaya bahwa sastra membawa nilai-nilai kemanusiaan yang universal (dengan standar-standar dari Dunia Barat) dan berlaku di setiap penjuru dunia. Di sisi lain, orang-orang Lekra percaya bahwa sastra mengandung nilai yang bisa jadi Borjuis maupun Proletar. Artinya, keduanya percaya sastra mengandung sebuah nilai entah untuk diajarkan maupun untuk dikritik.
Warisan ketiga Plato terletak di klaim bahwa karya sastra terkait dengan sesuatu yang lebih besar (Illahiah? Alamiah? ‘Syaitoniah’?). Dalam kritiknya, Plato menunjukkan bahwa perbedaan mendasar sastra dan filsafat terletak di sumber penulisannya. Seberapapun tak setujunya ia dengan jenis sumber produksi karya sastra karena dianggapnya tak dapat dikonfirmasi, namun tetap ia mengakui adanya hal yang lebih besar yang terkait dengan produksi sastra. Jika kita sedikit kembali ke belakang ke masa Romantik, diskusi tentang ranah (faculty) sastra ini sangat marak. Para penyair juga kritikus sastra (Colleridge, Goethe, Pater, dll.) dan filsuf (Kant, Schiller, dll.) rata-rata mencoba menghubungkan sastra dengan konsep-konsep abstrak yang lebih besar dari manusia seperti genious (kejeniusan), virtue (kebijaksanaan), sublime dan, tentu saja,beauty;empat konsep yang masih dibicarakan hingga detik ini.
Inilah tiga warisan Plato yang telah terus mengisi panggung perdebatan sastra selama lebih dari 2000 tahun.
_______________________
[i] (kata benda, Bahasa Jawa) Keluh-kesah sembunyi-sembunyi
[ii] (Kata kerja, Bahasa jawa) Berkeluh-kesah sembunyi-sembunyi
[iii] Saya kadang menggunakan istilah ‘puisi’ dan ‘puitika’untuk menyebut sastra. Kategori dan genre ‘sastra’ yang kita kenal sekarang kebanyakan merupakan warisan Renaisans. Di masa sebelumnya, orang cenderung menyebut ‘sastra’ dengan ‘poetry’ dan semesta pembicaraan mengenainya masuk dalam puitika.
[iv] (Habib, 2005, hal. 24)
[v] Ibid.
[vi] Ibid., hal. 28)
[vii] Ibid.
[viii] Ion adalah salah satu dialog Plato. Di dialog ini, tokohnya adalah Ion (seorang rhapsode) dan, seperti biasa, Sokrates. Kedua berdiskusi tentang makna dan fungsi teater (sastra). Menariknya, strukturIon dibangun berdasarkan urutan kritik Plato terhadap teater – mulai dari fanatisme Ion terhadap Homer hingga kebenaran apa yang sesungguhnya dibawa oleh penyair seperti Homer dan para penyambung lidahnya (rhapsode)sepertisi Ion.
[ix] Ibid., hal. 33
[x] Ibid., hal. 35
[xi] Seorang pemimpin yang baik, untuk polis Plato, adalah gabungan antara seorang filsuf – yang bertindak sebagai penjaga visi negara – dan seorang tentara (ksatria) yang berfungsi sebagai penegak visi tadi. Gabungan keduanya – yang di dalam buku Habib disebut ‘philosopher-king’ – inilah yang akan memimpin rakyat jelata seperti petani, tukang besi dan pedagang.
[xii] (Habib, 2005, hal. 21)
[xiii] Di buku Habib perumpamaan ini disebut “myth of the cave”
[xiv] (Habib, 2005, hal. 26)
[xv] Ibid., hal. 35


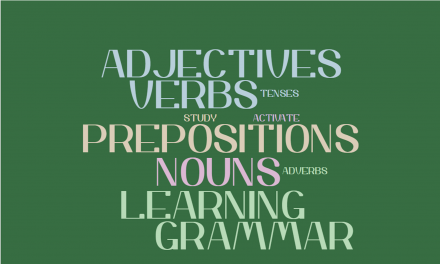



Komentar Terbaru