“Ah, kata-katamu retoris banget!” Hampir tidak mungkin jika kita tidak pernah mendapati kata-kata semacam itu di keseharian kita.
Tuduhan ‘retoris’ ini sering kali disematkan pada kata-kata yang dianggap ‘hiasan’ semata dan tidak bermakna karena tidak memberi sumbangan sesuatu apa pun pada percakapan yang terjadi selain untuk menggiring lawan bicara. Dalam ekspresi tersebut, saya menemukan pemahaman awal dan umum tentang retorika. Di sana, kata “retoris” ditempatkan untuk menyebut kata-kata yang diatur dengan baik demi mempengaruhi (persuasi) orang yang mendengar, namun tidak dibarengi dengan logika kebenaran yang sahih di dalamnya. Dalam arti, kata-kata tersebut tidak mementingkan kebenaran, karena yang terpenting adalah adanya usaha untuk membuat orang percaya. Pandangan tersebut jelas membuat kata retoris “seakan” memiliki imaji negatif. Penyematan makna negatif semacam itu ternyata bukan merupakan hal baru bagi kata “retoris” dan retorika karena hal itu sudah dimulai sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu!
Retoris, bentuk kata sifat dari retorika, diambil dari bahasa Inggris rhetoric yang berangkat dari bahasa Yunani rhetor. Dalam bahasa Yunani, rhetor berarti pembicara, dan kata tersebut mengacu pada seni public speaking. Public speaking dan sekadar “berbicara di depan umum” berdiri di ranah yang cukup berbeda, karena public speaking harus meliputi aturan-aturan tertentu yang dipakai oleh pembicara untuk berbicara di depan umum. Tidak berhenti hanya pada aturan-aturan yang terkait dengan pembicara, public speaking juga berkaitan erat dengan sang pendengar, karena tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pendengar melalui pembawaan konten secara intelektual, emosional, maupun dramatis. Karena itu, pembentukan makna dalam retorika tidak bisa terjadi sepihak, tetapi meliputi tiga pihak: pembicara, pendengar, dan konteksnya.
Pada perkembangannya selama lebih dari 2000 tahun, retorika telah diakui di dalam wilayah-wilayah yang dekat dengan keseharian kita.
Pertama, retorika dalam wilayah politik. Betapa pentingnya retorika pada wilayah ini karena kemampuannya untuk mempengaruhi, dan kita bisa lihat bagaimana para politisi di sekitar kita mempengaruhi dengan berbagai cara bicara, yang tidak lain tidak bukan merupakan hasil penggunaan retorika.
Kedua, wilayah institusi ilmu atau disiplin ilmu (filosofis). Pada wilayah ini, kesuksesan retorika diukur melalui seberapa sukses seorang pengajar mentransfer ilmu kepada yang diajar. Akan tetapi, fungsi persuasif retorika justru tak terlalu diterima di wilayah ini karena hal tersebut. Pentingnya usaha mempengaruhi dalam penyampaian tetap terbatasi dengan kebenaran dalam ilmu yang disampaikan oleh pengajar. Wilayah ini memperlihatkan bagaimana aspek penting retorika tunduk pada kebenaran, dan membuatnya berada di bawah logika dan metafisika. Kebenaranlah yang penting untuk ditangkap, bukan cara penyampaiannya. Jangan sampai hanya karena cara penyampaian yang bertele-tele, kebenaran yang ingin disampaikan justru tak tertangkap.
Ketiga, wilayah teologis, yang menunjukkan tunduknya retorika dalam hubungannya dengan pewahyuan atau yang transenden. Dalam arti, usaha untuk mempengaruhi yang penting dalam retorika berkelindan dengan kebenaran akan ajaran-ajaran teologis dan transenden, menjadikan aspek persuasif lagi-lagi tunduk dengan pentingnya kebenaran. Yang penting adalah wahyu Tuhan, bukan? Cara penyampaian lagi-lagi harus dikorbankan.
Yang terakhir adalah wilayah kritik sastra. Di wilayah ini, retorika memiliki posisi yang sangat kuat karena wilayah ini banyak meminjam bahasa dari retorika—sebuah hal yang dapat dimengerti mengingat fokus retorika berada pada kemampuan berbahasa, penggunaan kiasan-kiasan, dan relasi yang diciptakan antara pembicara atau pengarang dengan pendengar atau penikmat.[1] Namun, walaupun retorika mendapatkan posisi penting secara historis dalam kritik sastra, retorika tidak diajarkan secara khusus menjadi sebuah bidang studi tersendiri.
Pentingnya posisi retorika dalam mengawali kritik sastra itulah yang membawa M.A.R. Habib dalam bukunya A History of Literary Criticism: from Plato to Present (2005) menempatkan kisah retorika yang dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu dalam satu bab tersendiri. Perdebatan yang terjadi pada masa itu, yang diawali oleh kritik dari Plato, dan berlanjut kepada Aristoteles, menjadi landasan yang baik untuk memahami bagaimana kritik sastra bisa menjadi seperti yang kita ketahui sekarang, juga dengan segala perdebatannya.
Plato: Nilai Itu Universal pada Kontennya
Menurut beberapa sumber—Aristoteles, Cicero, dan Quintilian—seni retorika telah ditemukan pada 476 SM oleh Corax. Sejak saat itu, seni retorika telah menduduki posisi yang penting dalam masyarakat Yunani Kuno, terutama di bidang politik. Dapat dibilang, kemampuan untuk mengekspresikan diri, baik melalui wicara atau penulisan, telah menjadi salah satu batu fondasi bagi munculnya sistem demokrasi.
Telah menjadi hal yang wajar pada saat itu bahwa kelas yang berkuasa akan mengontrol masyarakat tidak hanya secara politis ataupun ekonomis, tetapi juga melalui instrumen-instrumen kebudayaan dan ide-ide atau konsep-konsep lain yang diinginkan, terutama bahasa. Maksudnya: kelas yang dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap bahasa, melalui kontrol terhadap gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan umum mengenai dunia yang diberikan kepada masyarakat, akan dapat merengkuh kekuasaan juga di bidang politik dan ekonomi. Kontrol tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa adanya penggunaan bahasa seperti dalam pidato di depan khalayak umum. Di sini retorika memainkan perannya yang penting bagi kelas penguasa.
Yang menarik dan harus dicatat, pada masa itu retorika masih digolongkan menjadi sebuah seni yang berdiri sendiri dan memiliki aturan-aturannya sendiri. Sebagai sebuah seni, para pengajarnya, atau yang disebut sophist, memberikan aturan-aturan penting seperti: pengaturan konten, pengaturan wicara-teks yang teratur, gaya (penggunaan bentuk kiasan atau metafora), kemudahan untuk diingat, dan cara penyampaian. Peran para sophist ini menjadi penting seiring dengan vitalnya retorika bagi legitimasi kekuasaan. Dengan kata lain, retorika menjadi instrumen untuk memberikan definisi kebenaran, kepribadian, dan moralitas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat oleh penguasa.
Kuatnya retorika dalam pemerintahan (dunia politik) itu bukan tanpa tantangan. Plato, melalui Dialogue-nya, yang selalu menghadirkan tokoh Sokrates dalam karya-karyanya, mengkritik “sesuatu-yang-masih-berupa-seni” itu tepat di titik tersebut (politik). Di dalam Gorgias, tokoh Sokrates—sebagai media bicara Plato—beranggapan bahwa argumen yang dibangun dalam bidang tertentu haruslah keluar dari para ahli di bidang tersebut, sedangkan para pelaku/guru retorika (rhetoricians)—seperti tokoh Gorgias dalam Gorgias—bukanlah orang yang ahli di bidang tertentu. Orang-orang seperti Gorgias hanyalah ahli dalam berbicara, sebagaimana pernyataan Gorgias yang tak dapat diterima oleh Sokrates “… the province of rhetoric is speech…”. Lebih ganasnya lagi, Sokrates menyimpulkan bahwa para pelaku retorika ini hanya dapat mempengaruhi pendengar-pendengarnya jika, dan hanya jika, para pendengar tersebut juga bukanlah seorang ahli di bidangnya karena “rhetorician is a non-expert persuading other non-expert”.[2] Argumen tersebut menunjukkan bahwa Plato ‘masih’ menitikberatkan konten saat memandang retorika.
Argumen tersebut mendapat tantangan dari Gorgias, salah seorang sophist penting, yang melihat retorika sebagai sebuah instrumen penting untuk konten itu sendiri. Gorgias di sini tidak bermaksud mengakui bahwa konten tak penting, tetapi ia lebih menitikberatkan kepada pentingnya usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi (cara penyampaian). Artinya, kebenaran mungkin tidak datang murni dari konten namun juga cara penyampaian. Itulah kenapa retorika dianggap perlu menjadi wilayah pembelajaran tersendiri yang terlepas dari bidang-bidang yang menggunakan jasanya.
Perdebatan konten-cara (bentuk) penyampaian ini luar biasa berpengaruhnya di kritik sastra. Karena perdebatan ini terbentuklah dua macam kritik sastra yang masih dipercaya oleh orang-orang. Perdebatan di ranah kritik sastra ini adalah antara kritik ala Plato yang fokus pada konten (didaktis)—sebagaimana diungkapkan di esai Plato beberapa minggu lalu—dan kritik sastra, yang terinspirasi dari para sophist, yang menekankan pada cara (bentuk) penyampaian. Kritik Plato yang lebih mengarah pada konten memperlihatkan bentuk kritik sastra yang berupa kritik-isi, sementara kritik ala para sophist memperlihatkan bentuk kritik sastra yang berupa kritik-bentuk.
Kini tampaknya ada dua tradisi yang terbentuk dan tak terdamaikan. Namun hal tersebut tak berlaku bagi satu orang pemikir yang tak ingin berlama-lama dengan perdebatan isi (didaktisme) – bentuk (persuasi) tersebut. Ia adalah Aristoteles yang selalu berusaha menemukan jalan tengah untuk semuanya.
Momen Penyatuan oleh Aristoteles
Perdebatan yang terjadi pada masa Plato tersebut mendapat perkembangan lebih lanjut di pemikiran salah satu muridnya: Aristoteles. Bentuk dialektika yang sebelumnya telah dimunculkan oleh Plato melalui pembelajaran terhadap pemikiran jaman pre-socratic menjadi acuan Aristoteles untuk memandang kembali retorika. Berbeda dengan gurunya yang dengan militan menolak retorika, Aristoteles justru melihat bahwa retorika ini penting karena dapat mempengaruhi sebuah kebenaran atau keadilan. Kemampuan retorika untuk menyatakan argumen yang tidak berdasarkan pengaturan premis-premis logis (filosofis dialektis Platonis), bukan berarti retorika sama sekali tidak membawa kebenaran seperti yang dituduhkan Plato.
Aristoteles menganggap retorika memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kebenaran. Ia menyatakan tersebut lewat konsep enthymeme-nya di bukunya Ars Rhetorica. Aristoteles melihat bentuk enthymeme sebagai dasar retorika. Ketika dialektika Platonis menggunakan silogisme yang premis-premisnya jelas dan terang, di sisi lain, retorika mengandalkan enthymeme yang merupakan silogisme dengan premis tak pasti, tak jelas, dan tak terang. Enthymeme ini biasanya berupa pengandaian dan imajinasi yang bukan sebuah kenyataan.
Dengan pandangan semacam itu, Aristoteles mencoba membela retorika sebagai sebuah ‘ilmu’ yang sejajar dengan filsafat (tentu Platonis) dengan metode dialektikanya. Dengan kata lain, Aristoteles mencoba merumuskan bahwa retorika dengan logikanya sendiri—dengan enthymeme—mempunyai landasan epistemologisnya sendiri. Dengan begitu, retorika tak boleh dipandang sebelah mata karena tampaknya retorika buka sekadar ‘cara penyampaian’.
Tidak berhenti sampai di titik epistemologis saja, Aristoteles juga membela retorika di titik praktis—sebuah hal yang mengingatkan kita dengan pembelaan Aristoteles terhadap puitika (sastra) di tulisan milik Pita Munthe di edisi sebelumnya. Bahkan Aristoteles menyebut retorika sebagai “deliberative study of morality.”[3] Hal tersebut dibeberkannya dengan beberapa contoh cabang retorika yang berguna secara praktis (sosial), yaitu:
- Deliberative rhetoric, yaitu retorika dalam bidang politik yang digunakan untuk memberikan nasihat mengenai kelebihan suatu keputusan atau pencegahan terhadap suatu akibat buruk yang akan terjadi dari suatu keputusan;
- Forensic rhetoric, yaitu retorika yang dipakai di pengadilan, dan merujuk pada hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, dengan tujuan memberikan tuntutan dan pertahanan untuk mendapatkan keadilan; dan
- Display rhetoric, yaitu retorika yang digunakan untuk mengkritik, memberikan pujian, atau memberikan pencemaran, untuk melegitimasi adanya kekuasaan tertentu pada masa kini.[4]
Menurut Aristoteles, semua cabang tersebut memiliki common goodness yang penting bagi masyarakat.
Sekali lagi, di sini kita disuguhi dampak pertentangan filosofis Plato-Aristoteles; Plato yang sangat Universal-oriented (theory of form) dan murid cerdasnya yang melihat pentingnya yang partikular bagi yang universal untuk ada di dunia konkret. Bedanya di sini retorika yang menempati posisi puitika. Dan hampir saja dengan puitika, retorika juga diperlukan bagi ide-ide besar untuk ada dan hadir di tengah masyarakat dan juga memiliki fungsi sosial selayaknya pengajaran untuk puitika (karya sastra).
Perjalanan Bentuk Berbicara yang Kemudian Menjadi Bentuk Kritik (Sastra)
Karena pembelaannya, Aristoteles lewat bukunya Ars Rhetorica menyumbangkan pembacaan lebih terhadap retorika berupa elemen-elemennya. Ia menyatakan ada tiga elemen oratorial tersebut, yaitu: topik umum, gaya, dan komposisi.
Topik umum menekankan pada pentingnya probabilitas, atau kemungkinan-kemungkinan, dan pemberian contoh-contoh. Seperti telah diketahui di atas, enthymeme adalah bentuk silogisme yang premis-premisnya tidak pasti. Bentuk silogisme ini dihadirkan melalui contoh-contoh kejadian di masa lalu untuk membentuk kemungkinan kejadian baru. Semakin banyak kejadian yang dapat dihadirkan, semakin tinggi pula kapasitas pelaku retorika dalam menarik garis contoh-contoh; maka akan semakin mudah premis-premisnya diterima oleh pendengar. Ini merupakan tandingan dari silogisme yang berdasarkan logika (dialektika), karena bentuk ini mengutamakan adanya kemungkinan-kemungkinan dalam pembuatan premis atau konklusi.
Yang kedua adalah gaya. Gaya lebih penting dibanding konten intelektual dalam retorika, karena gaya menentukan bagaimana pesan dapat diterima oleh penonton. Yang pertama dalam aspek ini adalah kejelasan, yaitu penggunaan metafora dan simile yang jernih sehingga mudah dipahami. Pendengar pun dapat berpikir dan mendapatkan kesenangan dari pengetahuan baru yang mereka terima. Aspek kedua adalah penggunaan bahasa yang tepat sehingga mudah dibaca dan mudah diomongkan kembali. Aspek ini berkaitan dengan penciptaan kalimat yang tidak terlalu panjang serta pemilahan yang tepat. Aspek ketiga adalah ketepatan, yaitu penggunaan ekspresi atau emosi pada bagian atau waktu yang tepat. Aspek ini diangkat dari aspek puisi, yaitu ritme. Pelaku retorika yang baik harus menyampaikan argumennya dengan ritme yang tepat, tidak seperti prosa yang kurang ritmis atau puisi yang terlalu ritmis. Aspek terakhir, yang bisa diraih dengan tiga aspek sebelumnya, adalah kelayakan.
Elemen oratorial terakhir adalah komposisi, yaitu bangunan retorika yang terdiri dari introduksi, narasi utama, bukti dari pembicara [yang bisa juga meliputi argumen tandingan], dan kesimpulan.
Tiga elemen oratorial yang dinyatakan Aristoteles ini kemudian menandai adanya pengaturan bentuk yang lebih jelas dibanding masa-masa sebelumnya. Konseptualisasi elemen-elemen ini juga kemudian berpengaruh besar pada dunia kritik sastra, terutama di sisi objek kritik. Pengangkatan sisi-sisi bentuk (penampilan) Aristoteles menjadi semacam pelengkap bagi kritik-isi yang dilakukan oleh Plato terhadap karya sastra. Kritik Platonis, yang terobsesi dengan yang-universal, cenderung fokus pada isi dan didaktisme, sedangkan Kritik Aristotelian, yang dekat dengan yang-partikular, merintis diskusi panjang mengenai pentingnya bentuk bagi seni.
Ya, dua nama ini: Plato dan Aristoteles. Dua nama yang warisannya akan terus dibicarakan dan mengawali tradisi-tradisi baru yang muncul selama 2000 tahun setelahnya. Kisah perdebatan dua nama, guru dan muridnya yang berbeda aliran pemikiran ini, menjadi poros banyak perdebatan.
[1] Habib, M.A.R. A History of Literary Criticism: from Plato to present. (UK: Blackwell Publishing, 2005) hal. 65
[2] Ibid, hal. 70
[3] Ibid, hal. 73
[4] Ibid, hal. 72




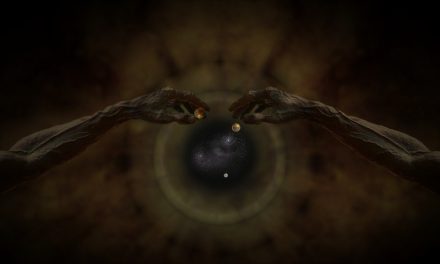

Komentar Terbaru