Di antara sekian banyak sastrawan ternama Nigeria, Wole Soyinka dan Chinua Achebe bisa dianggap sebagai yang paling terkenal dan berpengaruh, baik di dalam negeri maupun internasional. Di Indonesia, posisi mereka bisa kita sejajarkan dengan WS Rendra dan Pramoedya Ananta Toer. Keempat sastrawan tersebut, dengan caranya masing-masing, banyak mengeksplorasi kondisi keterjajahan negerinya dan memberi pengaruh pada cara pandang terhadap identitas masyarakatnya. Eksplorasi seperti yang mereka lakukan itulah yang kemudian melahirkan sebuah disiplin akademis bernama Kajian Pascakolonial pada awal dasawarsa 1990an. Tepatnya, eksplorasi macam apa yang dilakukan oleh mereka dan banyak sastrawan, seniman, dan intelektual lain sehingga bisa melahirkan satu disiplin akademis tersendiri? Tanpa mengesampingkan peran yang lain, pertanyaan itu akan coba saya jawab dengan mendekati tulisan-tulisan Chinua Achebe dan memfokuskannya di bidang sastra—awalnya, isu-isu dalam kajian ini memang muncul dari sastra.
Biasanya, kritikus sastra pascakolonial akan mendekati beberapa isu pokok. Pertama, menolak klaim universalisme dari sastra kanon Barat dan berusaha menunjukkan batas-batas pandangannya, terutama ketidakmampuannya dalam memahami secara empatik budaya yang berbeda dengan Barat. Kedua, terkait dengan tujuan itu, memeriksa representasi budaya liyan dalam sastra. Ketiga, menunjukkan betapa seringnya sastra diam dan mengelak untuk membicarakan persoalan-persoalan terkait penjajahan dan imperialisme. Keempat, mengedepankan pertanyaan-pertanyaan terkait perbedaan dan keragaman budaya dan memeriksanya dalam karya-karya sastra tertentu yang relevan. Selanjutnya, merayakan hibriditas, yakni situasi di mana individu atau kelompok secara bersamaan berada dalam dua budaya berbeda—penjajah dan lokal. Terakhir, dan yang dapat diterapkan di luar sastra, mengembangkan sebuah perspektif yang mengangkat pluralitas dan Keliyanan (Otherness) sebagai sumber energi dan potensi perubahan.[1] Beragam isu yang diperiksa oleh kritikus pascakolonial itu secara sederhana bisa dibagi menjadi dua kategori besar, yakni representasi (bagaimana Timur atau kawasan spesifik atau masyarakat tertentu direpresentasikan oleh Barat) dan eksplorasi-diri (mengangkat kondisi dan subjek pascakolonial).
Hampir semua isu yang diselidiki oleh kritikus pascakolonial di atas dibicarakan oleh Chinua Achebe baik melalui novel maupun esai-esainya. Achebe berbicara soal representasi Afrika dalam karya sastra dan mengangkat kebudayaan suku Igbo, salah satu suku terbesar di Nigeria, sebelum penjajah datang.[2] Ia berbicara soal universalisme dalam sastra, penggunaan bahasa dalam karya sastra Afrika, dan peran penulis di negara pascakolonial. Ia mengetengahkan posisi subjek di negara bekas terjajah dan merayakan hibriditasnya.
Tahun 1975 Achebe memberi kuliah di University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat, dengan makalah berjudul “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness.” Materi kuliah itu, seperti tertera jelas dalam judulnya, memeriksa rasisme yang ada di novel terkenal Conrad dimaksud, dan menyimpulkan bahwa “Conrad melihat dan mengutuk kejahatan eksploitasi imperial tapi anehnya tak menyadari rasisme yang justru menajamkan gigi imperialisme itu.”[3] Representasi Afrika di karya sastra, seperti yang dikritiknya itu, sebenarnya juga merupakan faktor yang mendorongnya untuk menulis novel. Saat belajar di Universitas, Achebe membaca berbagai novel yang berbicara tentang Afrika, dan merasa bahwa “kisah yang harus kita ceritakan tidak bisa diceritakan pada kita oleh orang lain tak peduli betapa berbakatnya ia atau betapa baik niatnya.”[4]
Hasrat sebagai insider researcher atau insider story-teller, hasrat untuk merepresentasikan diri-sendiri, memang sedang naik daun pasca-Perang Dunia II, saat negara-negara terjajah berjuang untuk, dan akhirnya berhasil, meraih kemerdekaan. Namun, kemerdekaan politik saja dirasa tidak cukup—apalagi ternyata penjajahan politik tidak lantas musnah; penjajahan lebih halus, yakni neokolonialisme, penjajahan ekonomi dan politik tanpa pendudukan langsung dan dilaksanakan melalui tekanan negara Barat, lembaga-lembaga keuangan internasional, termasuk berbagai funding tertentu, dan korporasi transnasional, lambat laun menggantikan kolonialisme “klasik.” Yang lebih mendalam, lebih susah dicapai dan butuh waktu lebih lama, adalah kemerdekaan budaya. Dengan kata lain, terciptanya budaya baru dan manusia-manusia baru. Negara baru yang lahir ternyata dikelola dengan mesin birokrasi kolonialis, bahkan kadang orang lokal lebih kejam perilakunya dari orang kulit putih yang dulu menjajah.
Di kalangan seniman dan intelektual Afrika, awalnya dan terutama jajahan Perancis, pernah muncul gerakan negritude, sebuah upaya untuk melawan dominasi budaya Eropa dengan menggali keluhuran dan kekhasan orang kulit hitam, sekaligus mengangkat blackness atau nigger sebagai sebuah kata yang tidak lagi bernada menghina.[5] Namun, gelombang gerakan yang bersifat romantis itu kemudian dipertanyakan. Persoalannya, ketika orang mencari kebudayaan asli Afrika, Asia, atau Jawa, misalnya, ia hanya menemukan jejak-jejak kabur, ditumpangi representasi kolonialis dan rasis dari penelitian-penelitian Barat, dan keadaan aktual masyarakat yang tidak lagi seperti dulu sebelum penjajah datang. Penjajahan berlangsung lama dan berhasil mengubah kebudayaan bangsa terjajah. Kebudayaan bangsa terjajah telah bercampur dengan kebudayaan penjajahnya. Istilah terkenalnya hibriditas. Atau dalam kata-kata Achebe, “[k]ita hidup di persimpangan berbagai kebudayaan.” Dulu dan kini. Hidup di persimpangan seperti itu punya potensi bahaya, tapi sekaligus potensi pencerahan. Bahaya “karena orang mungkin akan hilang-lenyap di sana bertarung dengan beragam semangat-mental yang berbeda,” tapi mungkin juga “ia beruntung dan kembali ke masyarakatnya dengan anugerah berupa visi yang profetik.”[6]
Hibriditas dan potensi pencerahan itulah yang dirangkul dan digenggam Achebe. Ia mengkritik universalisme Barat, terutama dalam sastra, dengan menegaskan bahwa ia “ingin kata ‘universal’ dilarang dipakai dalam diskusi mengenai sastra Afrika sampai tiba waktunya orang berhenti menggunakannya sebagai sinonim dari pandangan-picik Eropa yang sempit dan menguntungkan-diri-mereka-sendiri, sampai horizon mereka meluas dan mencakup seluruh dunia.” Akan tetapi, ia juga tidak menganjurkan pandangan-picik baru, chauvinisme baru. Ia paham dengan kondisi percampuran-budaya masyarakat Afrika, mengakui terciptanya negara-negara Afrika sebagai efek penjajahan, dan memilih untuk bersikap realistis, bahkan kadang-kadang praktis.
Dalam menulis novel, misalnya, ia memilih menggunakan bahasa Inggris alih-alih bahasa Igbo, Bahasa Ibunya, bahasa yang diakuinya lebih banyak dipakainya saat percakapan. Pilihan itu tampak praktis karena alasannya adalah potensi pembaca yang lebih luas, tetapi juga historis karena memandang bahwa persatuan Nigeria salah satunya dibentuk oleh bahasa Inggris.[7] Bagaimanapun, bahasa Inggris yang dipakai dan diekspresikannya adalah bahasa Inggris kreol, bahasa Inggris campuran, atau, mengutip Aschroft, dkk., more english than English.[8]Penulis Afrika, menurut Achebe, musti menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan pesannya dengan baik tanpa kehilangan fungsinya sebagai bahasa komunikasi internasional—maksudnya mungkin tidak terlalu banyak mengubah tatabahasa, ejaan, dll—tetapi juga tidak kehilangan karakter dari pengalaman khusus yang mau diungkapkan. Artinya, kalau bahasa Inggris itu ‘universal’ atau global sifatnya, maka ia harus juga mampu atau dimampukan untuk memikul beban pengalaman lokal penggunanya.[9]
Beragam pemikiran dalam berbagai isu penting masyarakat (bekas) terjajah itulah yang, salah satunya, membuat nama Chinua Achebe bersinar, menjadi rujukan wajib bagi orang yang memelajari Kajian Pascakolonial. Dalam konteks Indonesia, terutama saat datangnya gelombang otonomi daerah, bangkitnya wacana ‘kearifan lokal’, dan turisme yang mengumbar eksotisme, pemikiran-pemikirannya mengenai sastra dan budaya bisa kita jadikan pengingat akan relasi kekuasaan yang sedang berlangsung. Membuat kita lebih peka pada representasi, identitas, dan fungsi seniman/intelektual bagi masyarakat kita sendiri.
______________________________________________
[1] Disarikan dari Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory karya Peter Barry.
[2] Terkait novelnya Things Fall Apart, Achebe bilang “I would be quite satisfied if my novels (especially the ones I set in the past) did no more than teach my readers that their past – with all its imperfections – was not one long night of savagery from which the first Europeans acting on God’s behalf delivered them” (dari Morning Yet on Creation Day, 1975)
[3] Makalah ini kemudian muncul di kumpulan esainya Hopes and Impediments yang terbit tahun 1988.
[4] Lih. esai Chinua Achebe “Named for Victoria, Queen of England.” Mahakarya Achebe, Things Fall Apart, sebuah novel yang bercerita tentang kehidupan masyarakat suku Igbo sebelum penjajah datang, perlu diletakkan dalam konteks semangat merepresentasikan diri itu. Kita bisa menyandingkan novel itu dengan Arus Balik-nya Pramoedya Ananta Toer, baik dalam isi maupun semangatnya.
[5] Keterangan dari situs wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gritude, saya pikir cukup baik sebagai pengantar untuk melihat lebih jauh gerakan ini.
[6] Lih. esai Chinua Achebe “Named for Victoria, Queen of England”
[7] Lih. esai Chinua Achebe “The African Writer and the English Language”
[8] Lih. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature
[9] Pemilihan bahasa Inggris sebagai medium penulisan karya ini bertentangan dengan pendapat Ngugi Wa Thiong’o, seorang penulis Kenya, yang menganjurkan, dan melaksanakan, penggunaan bahasa lokal dalam menulis karya sastra. Kedua pilihan yang bertentangan itu, saya rasa, adalah persoalan cara saja. Dua-duanya mengklaim menggunakan cara terbaik untuk menyapa, sekaligus mendidik, masyarakatnya. Chinua Achebe, dalam esainya yang lain, “Novelist as Teacher,” memang mengeksplorasi fungsi pendidik dari sastrawan/seniman.
* Esai ini sebelumnya terbit di The Equator, Newsletter Yayasan Biennale Yogyakarta, Edisi 6, Agustus 2014. Versi digital Newsletter tersebut dapat dilihat di sini.


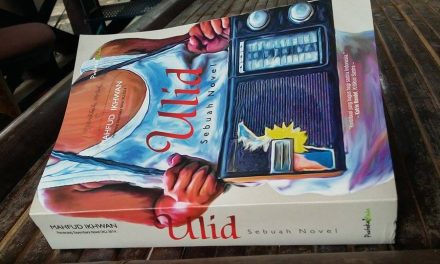

Komentar Terbaru